Sebatang rokok terapit manis di antara jemari manis dan tengahku. Jam menunjukan pukul sebelas malam. Musik menemani sepiku, dan aku menemani isi pikiranku. Berbicara dengan isi kepala sendiri adalah salah satu kebiasaan yang selalu aku sukai. Memikirkan hal-hal yang entah kenapa itu terjadi, lalu mulai berbincang dengan kepala. Misalnya saja, benarkah hidup selalu harus punya tujuan? Jika begitu, menjadi miskinpun tujuankah?
Asap mengepul, membumbung tinggi, menyebar memenuhi ruang lalu hilang. Bagaimana jika hidup ini seperti asap rokok? Selalu berusaha mengisi ruang-ruang yang kosong, lalu hilang? Kuteguk kopi tuk terakhir kalinya. Menikmati hangatnya, sembari berkhayal lagi. Hingga akhirnya, aku berpasrah pada simpul yang sebenarnya tak aku setujui. “Sudahlah! Tak perlu dipertanyakan lagi.”
***
Dering telponku berbunyi untuk kedua kalinya setelah yang pertama membangunkanku dari tidur. Aku mengangkatnya dengan keadaan setengah sadar.
“Jam berapa sekarang? Kau tidak ikut ujian hari ini?”
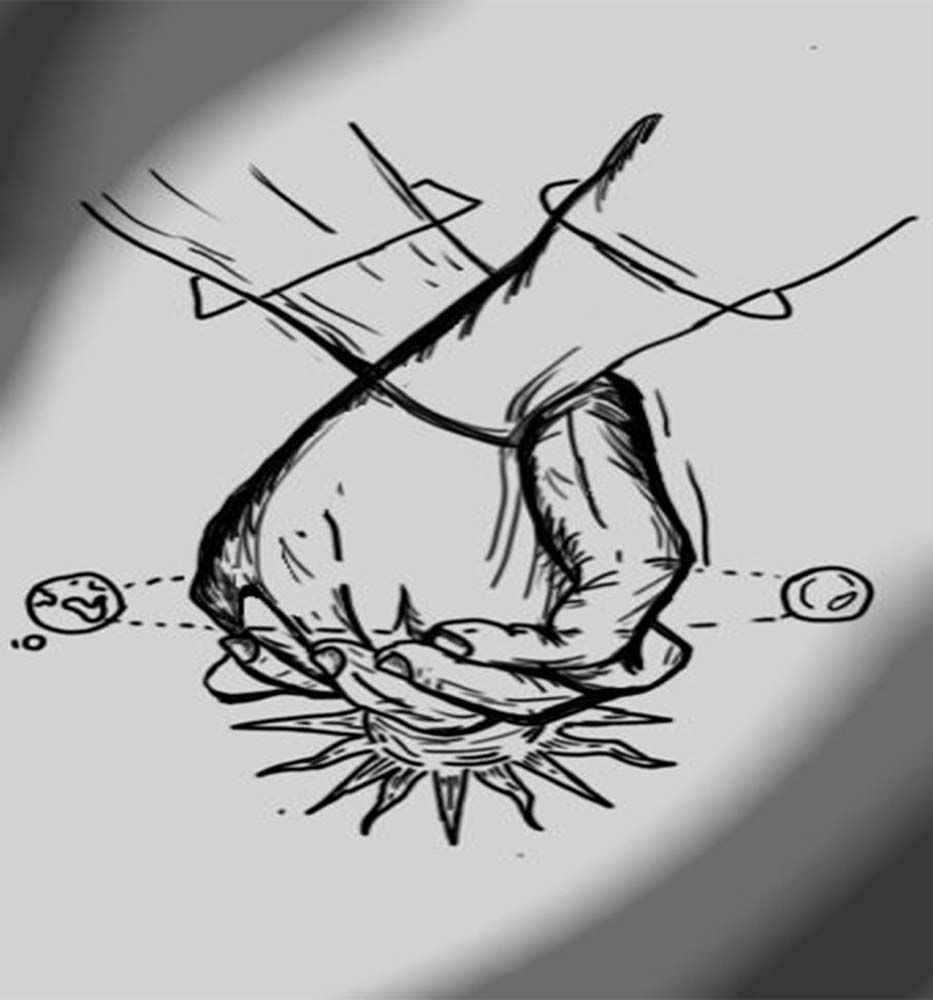
Kuusap mata. Terkejut melihat jarum jam menunjukkan pukul 09.17. Tak balas menjawab pertanyaan. Aku segera bangun dan secepat kilat membersihkan diri. Pukul 09.30, masih ada 20 menit lagi sebelum ujian dimulai. Aku segera bergegas menuju kampus.
Jika saja tidak ujian, sudah kuputuskan untuk bolos hari ini. Aku tiba tepat waktu. Dengan napas terengah-engah setelah setengah berlari menuju ruang kelas, aku masuk bersamaan dengan dosen yang akan memberikan ujian hari ini.
Belajar semalam sebelum ujian bukanlah hal yang menyenangkan bagiku. Belajar adalah proses. Proses adalah rutinitas. Jika tak mengerti, maka bertanya sampai paham. Jika tak tahu, maka membaca dan berlatih sampai mengerti, sampai tak terlupakan. Bahkan, tak hilang meski pelajaran berganti.
Ujian selesai, dan berhasil kuselesaikan semua soal. Bahkan, sebelum waktu berakhir.
“Terima kasih Nanda telah membangunkanku tadi.”
“Biar kutebak, pasti kau tak sempat menyikat gigi dan buru-buru datang kan?”
Tawa kami pecah di tengah keramaian mahasiswa yang sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing.
Nanda, perempuan yang kukagumi, tapi tak juga kumiliki. Perempuan yang kupuja, tapi masih sebatas harapan dalam doa. Senyumnya begitu indah. Lesung yang muncul sesekali di pipinya kadang bikin aku tenggelam. Entah kapan aku menyadari perasaan ini. Namun, yang pasti, setelah menyadari rasa ini, hariku serupa baris terakhir pada sepotong puisi menunggu; “Cara sederhana mencintai adalah menunggu”.
“Nando, aku pamit dulu ya. Harus menjemput adikku dulu.”
“Iya, baik Nanda. Hati-hati.”
Kami diakrabkan oleh hobi. Berdiskusi perihal bumi, tentang tutur dan tingkah manusia, berdengung dalam nada instrumen ‘river the flow’ yang begitu menggugah gairah. Atau, diam menikmati damai yang tercipta dari bisu kami.
Tidak pernah sekalipun kami berbagi cerita tentang keluarga, kerabat, atau bahkan, hubungan selain kami. Tapi bersamanya hilang segala luka, air mata, beban pikiran atau apalah yang mengganggu.
Telah kubaca banyak sekali buku perihal hidup, dinamika dan menghadapinya. Tapi tak juga kutemukan sepotong kalimat sebagai tempat kuberteduh sekadar sebagai prinsip. Bersama Nanda, aku mengerti bahwa kedamaian tercipta dari bisu paling diam. Kehangatan dituai dari percakapan paling panjang tentang keresahan jiwa-jiwa makhluk bernama manusia.
Sudah pukul 11.30, dan aku mulai merasa lapar. Aku pulang dengan senyum tersipu setelah mengingat kembali Nanda yang begitu teduh.
***
Hujan turun deras sekali sore ini. Langit gelap. Sesekali cahaya kilat menyambar disertai gemuruh guntur yang begitu keras.
“Nando… Ingatkah kau dulu sewaktu Ibumu masih hidup? Ketika hujan turun begitu deras, kita akan duduk bersama di sini. Ibu akan membuatkan minuman hangat lalu mulai menceritakan kisah perjuangan bagaimana melahirkanmu dulu?”
“Hahaha… Tentu saja aku ingat, ayah. Aku dilahirkan begitu susahnya. Karena aku anak pertama kan? Bukan karena sifatku yang keras kepala kan? Ibu selalu menggoda kala Ia kesulitan karena sifatku yang keras kepala. Padahal memang karena itu pengalaman pertama Ibu untuk melahirkan anak kan?”
“Hahaha… iya ya ya. Kau selalu menggerutu begitu tiap Ibu cerita.”
“Sedikit aneh ya. Padahal cerita yang sama selalu Ibu ulang. Tetapi tak pernah bosan aku mendengarnya.”
Aku anak tunggal. Pertama, dan tiada duanya. Ibu meninggal delapan tahun yang lalu karena menderita kanker selama setahun. Ibu dirawat dengan biaya rumah sakit yang begitu besar. Ayah sampai menjual hampir semua aset yang ia miliki. Mobil kesayangannya. Sebidang tanah warisan kakek yang rencananya akan dibuat kos-kosan juga dijual ayah. Ayah bahkan menjual pekerjaannya. Pangkatnya diturunkan karena lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ibu di rumah sakit daripada bekerja di kantor.
Ayah begitu mencintai Ibu. Sebegitunya hingga baginya semua harta yang habis tak sebanding dengan waktu yang masih bisa ia habiskan bersama Ibu sebelum ajal benar-benar dating menjemput Ibu. Aku ingat betul. Bagaimana Ibu yang meninggal dalam dekap ayah yang sedang berdoa memohon ampun akan segala kesalahan yang pernah terjadi, dan berterima kasih atas cinta yang tak terkalahkan oleh apapun di dunia, yang menyatu utuh dalam wujud diriku yang berdiri di antara mereka.
Sore ini hujan turun begitu derasnya. Aku dan ayah menikmati minuman hangat yang kami buat sendiri, dan mengenang kisah-kisah bersama Ibu dulu.
“Nando, tidak sekalipun ayah meragukan hidupmu kelak. Kau terlahir dengan otak yang cemerlang.”
“Ah ayah. Jangan begitu. Nasib selalu tidak tentu kan?”
“Hahaha… agak sulit ya berdiskusi perihal kemungkinan pada mahasiswa semester akhir.”
Ayah tertawa ringan, sembari menggosok-gosok dahi yang sudah sedikit keriput. Aku tersenyum. Menyulut sebatang rokok dan menariknya dalam-dalam kemudian menyemburkan segumpal asap yang langsung membumbung tinggi.
“Nando… ada yang ingin ayah sampaikan.”
“Ada apa ayah? Katakanlah. Anakmu mendengarkan, hehehe...”
Kami tertawa. Kuhisap rokok dalam-dalam lagi. Menikmati asapnya sembari menyeruput kopi yang masih hangat.
“Nando… ayah percaya akan kekuatan cinta. Pada siapa kau percaya, pada siapa harapanmu tertuju, pada ia kelak kau kan bersanding. Ayah percaya pada ibumu. Padanya segala doa ayah memohon agar bersamanya kelak. Adakah wanita yang kau kagumi, Nando?”
Aku terbatuk menelan asap rokokku sendiri, mendengar pertanyaan ayah yang begitu tiba-tiba. Wajah ayah serius saat melontarkan pertanyaan itu. Kuseruput lagi segelas kopi yang mulai dingin. Memperbaiki posisi dudukku. Sedikit tertunduk bingung. Aku lalu menjawab dengan pasti sedikit malu.
“Ada seorang wanita yang kukagumi ayah. Entahlah… kami tidak pernah berbincang tentang kehidupan pribadi masing-masing. Tetapi aku merasa nyaman bersamanya.”
Ayah terdiam mendengar jawabku. Aku mengharapkan ayah sedikit tertawa dan mulai menggodaku layaknya seorang sahabat yang sedang mendapati kawannya sedang kasmaran.
“Nando! Maafkan ayah tidak memberitahukanmu lebih awal terkait pesan Ibumu. Ada sebuah permintaan Ibu padamu yang dititipkan pada ayah sebelum Ibu meninggal. Ibu ingin agar kau kelak menikahi putri sahabatnya, mereka telah berjanji akan hal ini sejak lama.”
Aku terdiam. Tak percaya betapa egois permintaan yang satu ini dari ibu. Ayah pun terdiam. Seolah ayah tengah menenangkan diri dari beban akan rasa bersalah padaku. Ayah menyeruput teh yang sudah dingin dalam gelas di tangannya. Aku masih tak berkomentar. Ayah lalu melanjutkan.
“Ayah menolak keras permintaan Ibu. Ayah ingin agar kau sendiri yang memilih siapa yang akan bersanding bersamamu kelak. Ibu memohon agar menyampaikan permintaan padamu, sebelum akhirnya terlalu jauh kau menyimpan rasa pada seorang lain yang bukan pilihan Ibumu. Ini adalah permintaan sedikit egois Ibumu yang juga manusia. Ia hanya ingin yang terbaik untukmu. Ayah tidak akan memaksa.”
“Sedikit egois? Sudah kuyakinkan diri untuk jujur dan terbuka pada ayah, bahwa ada seorang wanita yang kukagumi. Hentikan drama ini ayah. Kita bukan lagi hidup di zaman kerajaan. Seolah dua manusia sedang ditawar atas nama cinta.”
“Nando… ini adalah permintaan Ibumu yang telah tiada. Permintaan sebeluum ia meninggalkan kita. Egois memang, tetapi Ibu menginginkan yang terbaik untukmu. Sahabat ibumu sudah menghubungi ayah untuk mempertemkanmu dan putri mereka minggu depan. Pertimbangkanlah Nando.”
Ayah bangkit berdiri meninggalkanku setelah mengatakan hal itu.
“Satu minggu? Bagaimana rasa yang telah tumbuh sekian lama dapat kuhilangkan dalam waktu satu minggu tuk dapat membuka hati kepada seorang wanita lain yang bahkan tidak kukenali ?” Batinku kesal penuh geram.
Aku menarik rokok dalam-dalam tuk terakhir kalinya, lalu menghembuskan asapnya. Kali ini tak kunikmati asapnya. Hanya kuperhatikan bagaimana ia memenuhi ruang yang kosong lalu hilang. Barangkali benar hidupku serupa asap rokok, hanya memenuhi keinginan Ibu, lalu hilang kelak.
Hujan meredah. Bau tanah yang basah menyambar. Aromanya begitu damai. Damai sekali.
***
Malam berganti pagi, pagi menjelma siang, lalu malam kembali. Sudah tiga hari aku menghindari diri dari Nanda. Pesan-pesan yang Ia kirimkan tak kubalas. Telephone darinya pun tak kuangkat. Aku sungguh merasa tersiksa. Pernah kuingat percakapan kami di suatu sore seberang jalan menuju kantin.
“Nando… aku ingin menjadi manusia paling bebas dari siapapun. Aku ingin menjadi perempuan paling merdeka dari siapapun.”
“Seperti apa kemerdekaanmu?”
“Berjalan. Berlari. Tertawa. Menangis. Atau apapun kulakukan asal seturut mauku.”
“Itu bukan merdeka Nanda. Merdeka berarti kau membuat batasan-batasan lalu menjalaninya dengan niat hati yang tulus tanpa sekalipun keluar dari batas yang kau ciptakan. Terdengar seperti terbelanggu memang, tetapi merdeka tak berarti bebas. Hanya kematian yang membebaskanmu dari segalanya. Satu langkah yang kau buat memikul satu tanggung jawab, karena kau terikat pada sesuatu yang bernama kehidupan.”
Sebatang rokok terapit manis di antara jemari manis dan tengahku. Jam menunjukan pukul sebelas malam. Musik menemani sepiku. Dan, aku menemani isi pikiranku. Aih Nanda, kali ini aku sungguh ingin menjadi manusia paling bebas. Paling merdeka dari siapapun di dunia ini.
Aku anak tunggal. Pertama, dan tiada duanya. Aku putra Ibu. Satu dan seutuhnya. Aku menyayangi Ibu seperti ayah yang sangat mencintai Ibu. Seperti ayah yang mengorbankan segalanya untuk Ibu. Barangkali akupun perlu sedikit mengorbankan perasaanku pada kehendak Ibu.
***
Sudah seminggu sejak percakapanku dengan ayah sore itu. Hari ini aku dan ayah akan pergi menemui sahabat Ibu beserta putrinya. Seminggu tanpa kabar kepada Nanda. Namun tak pernah sekalipun kulupa menyebut namanya dalam doa.
“Terima kasih karena kau mau menuruti permintaan egois Ibumu.”
Aku hanya diam, mengangguk membalas ayah. Hari cerah, awan membentuk rupa-rupa yang abstrak. Langit biru terbentang begitu luas sejauh mata memandang. Aku dan ayah berangkat menggunakan mobilnya yang Ia beli beberapa bulan yang lalu.
Setengah jam perjalanan, akhirnya kami tiba. Rumah berdinding putih. Pohon besar rindang meneduhkan. Bunga-bunga tampak indah. Kurasakan begitu damai suasana rumah ini. Seorang wanita seumuran ayah datang dan memperkenalkan diri sebagai Tanta Lala. Ia sahabat Ibu sejak berada di bangku sekolah dasar.
“Ayo masuk Nando.” Senyumnya ramah sekali. Ia begitu senang melihatku, seolah ia bertemu sosok Ibu dalam diriku.
“Matamu mirip sekali dengan mata Ibumu.” Ucap Tanta Lala sembari mengantar kami ke ruang tamu. Aku hanya tersenyum mendengar ucapannya. Dari ruang tamu dapat kulihat samar seorang wanita yang seumuran denganku bersama sosok ayah yang sedang sesekali menggoda putrinya.
“Rian, Nanda. Kemarilah. Riki dan ptranya sudah datang.” Aku terkejut mendengar nama Nanda dipanggil.
“Nanda? Nanda Anastasya?” Aku bertanya memastikan pada Tanta Lala.
“Iya, Nanda. Kalian sudah saling kenal kan? Nanda sering menceritrakanmu pada kami. Aku dan suamiku sudah menyampaikan kepada Nanda perihal janji egois yang aku dan Ibumu buat dulu. Nanda menolak dengan keras awalnya, namun tak kami sangka Ia menganggumi lelaki yang adalah putra Sania, Ibumu, sahabat ku.”
Mukaku merah padam mendengar Ibu Nanda yang jujur mengatakan kalau Nanda menyukaiku. Ini cinta. Ini rotasi cinta. Pada siapa kau percaya. Pada siapa segala harapmu tertuju. Padanyalah kelak kau kan bersanding. Sejauh apa pun kau melangkah. Mencoba menghindar sejauh mungkin. Kau hanya akan berputar mengelilingi seorang yang kau percaya. Hingga akhirnya kau berhenti untuk waktu yang lama. Untuk selamanya.
Hari itu langit begitu cerah. Awan membentk rupa-rupa abstrak. Hari ini kerinduanku pada Nanda terbayar. Nanda, perempuan yang kukagumi, kini kumiliki. Perempuan yang kupuja, kini tidak sebatas harapan dalam doa. Senyumnya begitu indah. Lesung yang muncul sesekali di pipinya bikin aku tenggelam. Selalu. Dan, senatiasa.
***
Pagi begitu cerah. Langit biru membentang sepanjang mata memandang. Awan putih bergumpal membentuk rupa-rupa abstrak. Seorang wanita dengan tatapan teduh datang dan mendekatiku, mengenggam tanganku, tersenyum dan diam menatapku. Damai.
“Nando, apa tujuan hidupmu?.”
“Entahlah Nanda.”
****************THE END****************



























Cerpen…iya cerpen…sudah lama kutak menjamahnya…dari tahun tidak enak. Jamanku ada majalah remaja: Hai atau Anita Cemerlang…
Kini jaman tlsh berubah…
Generasi kini enggan membaca cerpen…
Apaksh memang generasi kini tak memerlukannya???
Terima kasih bung Kanis. Terima kasih ceroen-nya.