Oleh: Defri Ngo
Alumni STFK Ledalero
Tanggapan saya berjudul Kritik atas Kritik yang Kritikal (KKK) pada 10 November 2022 lalu mendapat balasan kilat. Tanpa menunggu banyak waktu, Rinto Djaga kembali membuat tanggapan berjudul ‘Panggung, Alur, dan Tubuh: Tidak ada yang Bisu di dalam Teater (PAT)’. Jika Rinto cukup cermat, PAT sesungguhnya lebih berisi penjelasan tambahan terhadap artikel terdahulu dibanding kritik yang sistematis terhadap saya. PAT tidak perlu diperdebatkan karena tidak menghadirkan pembacaan yang baru.
Meski demikian, saya perlu menerangkan kembali dua gagasan pokok saya dalam KKK, berikut memberi alternatif pandangan untuk memahami hakikat teater. Saya konsisten dengan posisi tilik saya sebagai orang yang berada di luar teater Cermin. Tanggapan saya merujuk pada artikel pertama Rinto yang dinilai problematis dan kontradiktoris.
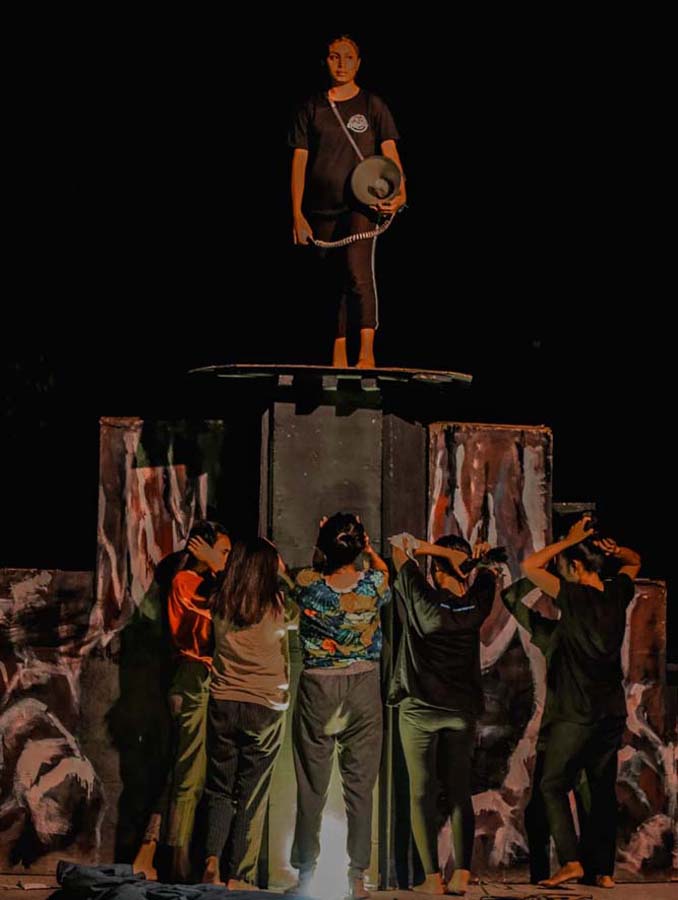
Dalam perspektif hermeneutik Hans G. Gadamer, model tanggapan yang demikian memiliki kemungkinan mengingat teks memiliki otonominya sendiri. Teks secara in se menyatakan dirinya sebagai teks yang dapat lepas dari tinjauan penulis (Hasyim Hasanah, 2017:16). Pembaca memiliki keluasan interpretasi untuk meninjau kembali, berikut menggugat hal-hal yang dinilai cacat dalam sebuah teks.
Dasar Perdebatan
Dalam artikel pertamanya berjudul ‘Mencari Suara Korban dari Teater Cermin Aletheia’ (MSKTCA), Rinto menguraikan sejumlah persoalan yang termuat dalam pementasan teater Cermin.
Saya mencatat terdapat setidaknya dua persoalan serius yang diangkat Rinto dalam artikel tersebut. Pertama, soal multiplisitas dan ambiguitas dalam mengolah lakon. Istilah multiplisitas (multiplicity)menunjuk pada situasi di mana terdapat keberagaman persoalan dalam sebuah lakon. Sedangkan, istilah ambiguitas berarti pengulangan terhadap cerita-cerita yang sama.
Bagi Rinto, multiplisitas dan ambiguitas berdampak pada hilangnya pesan yang hendak disampaikan dalam teater Cermin. Pembaca tidak memiliki suatu horison tunggal untuk menyatukan potongan-potongan adegan dalam setiap lakon. “Semua seperti gambar acak yang ditampilkan dari beberapa potongan cerita,” keluh Rinto dalam MSKTCA (Paragraf 4 baris 13). Lebih jauh, “apa pesan yang hendak disampaikan dalam potongan-potongan adegan semacam itu”?
Terhadap keluhan tersebut, saya dalam artikel pertama berjudul Kritik atas Kritik yang Kritikal (KKK) menimpal, “multiplisitias dan ambiguitas justru diperlukan untuk menegaskan kemendesakan atau urgensi isu” (Paragraf 6 baris 4). Sebab, seni bukanlah bahasa yang cukup universal. Bahasa seni lahir dari pengalaman subjektif individu dalam ruang lingkup yang parsial. Hanya individu-individu yang memiliki pengalaman serupa yang dengan mudah menangkap maksud dari sebuah karya seni.
Pandangan ini masih dapat diperiksa, sebagai misal dengan mengajukan tanggapan bahwa selain aspek pengalaman, seni juga membutuhkan aspek pengetahuan. Kekuatan pengetahuan akan menghantar subjek untuk memahami maksud seni. Dalam bahasa Theodor Adorno (1969: 254), pengetahuan terhadap objek (karya seni) membawa subjek lebih dekat dengan aksinya untuk menyobek tenunan kerudung dari objek. Individu akan menangkap maksud seni yang sanggup mengubah pikiran dan perasaannya.
Kedua, soal kontingensi bahasa korban. Dalam MSKTCA, Rinto menyoroti kebisuan para korban dalam lakon Cermin. Perasaan para korban sebagai manusia dan perempuan tidak mendapat tempat di atas panggung. “Kebisuan para korban, sesaknya pertunjukkan dengan berbagai peristiwa dan kejadian membuat jalanya pementasan terkesan monoton” (Paragraf 10 baris 1).
Saya memahami pernyataan tersebut sebagai usulan agar lakon Cermin sebisa mungkin menampilkan suara para korban. Cermin perlu mengeksplorasi persoalan-persoalan yang dialami oleh para korban agar penonton dapat memetik pesan utama pementasan. Pertanyaan saya, bagaimana korban kekerasan dapat berbicara dengan bahasa mereka? Apa alat tutur yang paling mujarab untuk membahasakan maksud hati para korban?
Korban kekerasan yang ditampilkan dalam teater Cermin adalah sosok-sosok yang bisu. Bahasa mereka bersifat terbatas (kontingen). Richard Rorty (1989: 94) dalam Contongency, Irony, and Solidarity membenarkan bahwa korban kekerasan dan orang-orang yang menderita tidak memiliki banyak bahasa. Mereka terlalu menderita untuk menyusun kata-kata sendiri (Rorty, 1989: 94).
Dalam analisis semiotik, kebisuan sesungguhnya memiliki bahasanya sendiri. Kebisuan menjadi tanda bahwa individu sedang direpresi dan diintimidasi oleh otoritas tertentu. Ketika bisu, para korban sesungguhnya hendak mengungkapkan dan membahasakan sesuatu. Bahasa mereka berisi ungkapan hati agar orang tergerak untuk memberikan bantuan dan pertolongan.
Model pembacaan yang demikian kerap hilang dari pikiran para penonton yang selalu berharap mendapatkan jawaban dalam teater. Mereka menghendaki agar teater menjadi ruang yang sanggup memberikan jawaban langsung terhadap sebab dan akibat utama persoalan. Persis demikianlah keinginan Rinto dalam pementasan Cermin.
Konstruksi Cerita dan Interaksi Simbolik
Setelah mendapat catatan kritis atas MSKTCA, Rinto menyusun tanggapan balik dalam uraian berjudul PAT. Sebagaimana dicatat Rinto, PAT memusatkan perhatian pada dua hal utama, yakni konstruksi cerita dan interaksi simbolik antara pelakon dan penonton.
Penjelasan tentang konstruksi cerita terarah pada kritik soal multiplisitas dan ambiguitas mengolah lakon. Sedangkan interkasi simbolik menjadi jawaban atas kritik saya terkait kontingensi bahasa korban.
Rinto merangkum pemahaman bahwa multiplisitas dan ambiguitas serta kontingensi bahasa dapat “disembuhkan” dengan memperbaiki konstruksi cerita. Kelihaian sutradara dan pelakon diperlukan untuk menampilkan bangunan cerita yang runtut, sistematis, dan dialektis. Penjelasan terhadap keduanya bermuara pada upaya untuk membangun sebuah format pertunjukkan yang menarik. Saya akan menjelaskan kedua hal yang disampaikan Rinto dalam uraian berikut.
Pertama, soal konstruksi cerita. Secara sederhana, konstruksi berarti aktivitas membangun sebuah dinamika pertunjukan sehingga menimbulkan konflik dan tegangan. Konstruksi cerita yang menarik memudahkan tersampainya pesan kepada para penonton.
Lebih lanjut, konstruksi cerita harus memiliki fokus yang jelas dan terarah pada maksud utama pementasan. Dengan menghadirkan keberagaman adegan yang juga diulang-ulang, penonton justru tidak menangkap pesan utama yang hendak disampaikan dalam teater. “Semua itu menjadi repititif dan monoton, bukan terletak pada multiplisitas, tetapi pada konstuksi cerita yang dibangun,” tulis Rinto dalam PAT (Paragraf 4 baris 3).
Dalam rumusan yang lain, saya dapat mengatakan bahwa multiplisitas dan ambiguitas diperlukan sejauh konstruksi cerita terarah pada fokus yang jelas. Sebuah seni pertunjukkan seperti teater memang harus dilandaskan pada suatu titik pusat sebagai locus cerita. Seperti novel, fokus cerita sebagaimana dimaksud Rinto berarti pengolahan alur cerita yang selalu terarah pada inti persoalan.
Cermin yang mengangkat tema kekerasan sebisa mungkin mengungkap sebab persolan dan akibat yang dialami para korban. Salah satu cara yang ditawarkan Rinto adalah mengenai pengolahan psikis dan emosi pelakon.
Kedua, interaksi simbolik antara pelakon dan penonton. Dalam upaya menjawab kritik saya soal kontingensi bahasa, Rinto memproposalkan pentingnya interaksi simbolik antara pelakon dan penonton. Saya memahami interaksi simbolik sebagai “komunikasi tanda” yang sanggup membangkitkan kesadaran dan ingatan dalam diri pelakon dan penonton. Pelakon tidak saja bergerak sesuai dengan tuntutan sutradara, tetapi sebisa mungkin menghayatinya sebagai bagian yang sungguh dialami dalam hidup.
Sebaliknya, penonton tidak saja berperan memberikan applaus, tetapi dapat menyindir kecenderungan pelakon yang terkesan “menyusu” pada sutradara.Relasi dialektis yang ditandai dengan penggunaan tanda menjadikan teater sebagai panggung kehidupan yang dipenuhi dengan persoalan, penderitaan, dan tangisan.
Kini, hal yang menjadi tugas sutradara -menimbang ulasan soal konstruksi cerita- adalah membangun model pertunjukan yang sistematis dan tetap terarah pada maksud utama Cermin. Fokus cerita harus menjadi pegangan sutradara dan pelakon agar rangkaian pementasan Cermin tidak saja memuat “potongan cerita”, tetapi juga mengafirmasi “maksud utama” pementasan.
Apa yang Perlu Diubah dari Cara Berpikir Kita tentang Teater?
Dengan membuat pertimbangan pada dua tanggapan Rinto, saya hendak menunjukkan penolakan saya terhadap MSKTCA dan penerimaan terhadap PAT. Gagasan-gagasan dalam MSKTCA tidak memiliki basis argumentasi yang jelas, berikut membingungkan saya sebagai pembaca. Penolakan terhadap multiplisitas dan ambiguitas serta kontingensi bahasa hanya menghantar orang pada penilaian yang sepihak terhadap pementasan Cermin. Orang akan menilai Cermin sebagai lakon yang gagal dalam membawa pesan terhadap orang lain. Padahal, kegagalan Rinto dalam menguraikan detail penjelasan yang seharusnya perlu mendapat perhatian.
Penolakan terhadap MSKTCA merupakan bentuk perlawanan terhadap gagasan yang terlampau “serta merta” dan “remeh temeh” dalam memandang teater. Aspek multiplisitas dan ambiguitas serta kontingensi bahasa para korban perlu diketahui bersama agar penilaian terhadap teater menjadi lebih seimbang dan menyasar pada inti persoalan.
Di pihak lain, penilaian-penilaian umum seperti lakon yang repetitif, monoton, dan bisu perlu diperiksa kembali mengingat teater bukanlah ruang untuk menunjukkan kebenaran pandangan. Hal yang repetitif dalam pandangan Rinto, misalnya merupakan cara sutradara untuk menunjukkan apa yang dalam KKK disebut sebagai kemendesakan isu dan urgensi cerita.Refleksi penonton tetaplah subjektif dan tidak memiliki ruang lingkup yang luas. Pertanyaannya, apa yang perlu diubah dari cara berpikir kita tentang teater?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya berhutang budi pada gagasan estetika Theodor Adorno dan kontingensi bahasa dalam perspektif Richard Rorty. Dalam pandangan Adorno, pengenalan tentang seni harus menempatkan aspek pengalaman pada pihak yang lebih dominan daripada pengetahuan. Pengalaman subjek sebagai korban akan berbicara dengan bahasa yang lebih menggugah dibanding pengetahuannya sendiri.
Batas antara pengalaman dan pengetahuan berbeda. Jika pengalaman bertolak dari kenyataan riil yang menggugah kejiwaan subjek, pengetahuan justru menempatkn analisis teoritis untuk mengungkap kebenaran. Bagi Adorno, aktivitas pengetahuan sebagian besar merupakan penghancuran dengan menggunakan kekerasan terhadap objek (Adorno, 1969: 254).
Pengetahuan akan mereduksi derajat seni hanya pada kutub-kutub yang bisa dipahami dengan akal sehat. Pada titik ini, estetika tidak dapat mencapai tujuannya dengan membuka kebenaran yang ada di balik karya seni (Syakieb Sungkar, 2022: 42).
Gagasan Adorno tentang estetika menjadi sangat penting untuk memahami hakikat seni secara umum dan teater secara lebih khusus. Penekanan terhadap aspek pengalaman perlu diperhatikan jika individu ingin masuk ke dalam realitas panggung dan teater. Individu tidak dapat memaksakan pengetahuannya untuk diikuti oleh orang lain, sebab pengalaman tentang seni selalu bersifat subjektif.
Dengan pemahaman seperti ini, penanggap atau kritikus sastra sekalipun perlu menggunakan pendekatan alternatif untuk memahami karya sastra. Kosa kata-kosa kata alternatif perlu dihidupkan agar sastra, secara khusus teater, menjadi ruang belajar bersama bagi setiap individu.
Jika Adorno berbicara soal dimensi pengalaman sebagai syarat memahami karya seni, maka Rorty mendesak pentingnya pemahaman terhadap kontingensi bahasa. Penjelasan tentang kontingensi bahasa dimulai dari kritik Rorty terhadap geliat modernisme yang menawarkan pandangan tentang validasi pengetahuan dan kebenaran. Kesadaran tentang sifat bahasa yang kontingen berarti mengakui bahwa dunia beserta segala pandangannya bersifat terbatas. Hal yang sama dialami oleh para korban kekerasan. Mereka memiliki bahasa yang terbatas untuk mengungkapkan keluhan hati. “Mulut mereka sudah terpenjara ketakutan. Tubuh mereka diintimidasi otoritas” (KKK, paragraf 8 baris 2).
Aspek kontingensi bahasa sebagaimana dimaksud Rorty kerap ditampilkan dalam sejumlah pertunjukan teater yang mengangkat tema seputar kekerasan. Tujuannya untuk mengungkap pergulatan hati para korban yang disesaki oleh berbagai ancaman. Rupanya, hal yang sama yang menjadi pertimbangan dari sutradara teater Cermin ketika menyusun naskah. Para korban dibiarkannya bisu. Dalam kebisuan, mereka rupanya sedang mengungkapkan sesuatu. Dalam kebisuan yang sama, mereka sedang berbicara. Pertanyaannya, apakah kita punya telinga untuk mendengarkan suara mereka? Apakah hati kita terbuka untuk berpaling pada bahasa mereka yang terbatas? ***
DAFTAR PUSTAKA
-Adorno, Theodor. 1969. Critical Models: Intervension and Catch Worlds. Terj. Henri W. Pickford. New York: Columbia University Press.
-Hasanah, Hasyim. “Hermeneutika Ontologis-Dialogis Hans Georg Gadamer”. Jurnal At-Taqqadum, No. 9, Vol. 1, 2007.
-Rorty, Richard. 1989. Contingency, Irony, and Solidarity. New York: Cambridge University Press.
-Sungkar, Syakieb. 2022. Seni sebagai Pembebasan. Jogjakarta: Penerbit Circa.






























