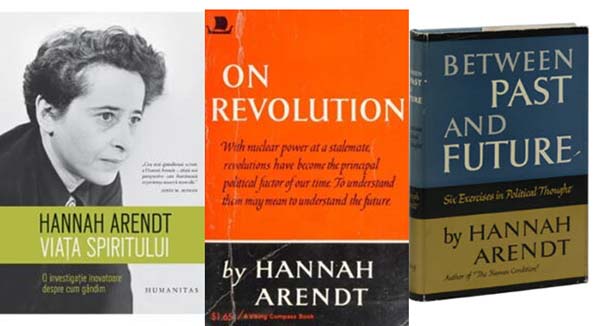Oleh Edi Riyadi Terre
Aktivis HAM dan Demokrasi, Alumnus STF Driyarkara
Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara
KALAU “kebebasan adalah alasan adanya politik”, sementara pluralitas adalah kondisi inheren dan bukan sekadar prasyarat mutlak kehidupan politik, maka kebebasan dan pluralitas adalah dua sisi mata uang dan kebalikan dari kedua hal itu (ketidakbebasan dan ketunggalan) adalah apolitis. Manusia (man) tidak manusiawi (human) kalau tidak politis. Tapi politik bukanlah sebuah alternatif bagi kehidupan manusia, melainkan sebuah pencapaian puncak eksistensinya, sebuah apa yang saya sebut sebagai “konstruksi eksistensial” yang memungkinkan manusia menemukan kebenaran bahwa ia adalah manusia—politik adalah sebuah aletheia, disclosure, penyingkapan. Penyingkapan kebenaran itu terjadi melalui tindakan sebagai salah satu aktivitas utama dari tiga bentuk vita activa (dua lainnya adalah kerja dan karya, dan keduanya tidak politis). Di satu sisi, politik adalah ruang bagi tindakan untuk dimengerti sebagai tindakan, di sisi lain tindakan hanya dimungkinkan karena manusia itu bebas dan plural. Dengan demikian, politik adalah suatu “konstruksi eksistensial”—mayoritas komentator Arendt menyebutnya “artifisial” yang hemat saya agak mereduksi karakter eksistensialisme dalam filsafat politik Arendt—yang di satu sisi dimungkinkan karena kebebasan dan pluralitas manusia-manusia yang terwujud dalam tindakan dan, di sisi lain, tindakan itulah yang “merawat” kebebasan dan pluralitas.
Demikianlah kira-kira yang dapat saya padatkan dari keseluruhan pemikiran Hannah Arendt bukan tentang politik melainkan tentang “manusia” yang seharusnya adalah “manusia politik”. Dikatakan seharusnya karena dua hal: pertama, politik bukanlah sebuah proses natural (Aristotelian) dan sosiologis (Hobbesian), melainkan kultural; jadi bukan sebuah keniscayaan alami atau keniscayaan hasrat individual dalam kesosialan manusia, melainkan sebuah upaya sadar dan transformatif. Kedua, kondisi yang memungkinkan untuk pencapaian eksistensi manusia politik itu selalu terancam oleh hasrat ketunggalan yang melahirkan ketidakbebasan, sebagaimana dipraktikkan oleh rezim totaliter dan demokrasi liberal yang salah arah.
Tindakan adalah ekspresi hakikat transformatif dan transendental manusia pada ketakterdugaan dan ketidakdiharapkanan. Dari pernyataan terakhir ini, orang bisa salah mengerti teori tindakan Arendt dengan mengatakan bahwa totalitarianisme (karena ketakterdugaan dan ketakdiharapkanannya) adalah “anak haram” yang niscaya lahir dari tindakan manusia. Namun saya tekankan bahwa teori tindakan Arendt tidak dapat dibaca lepas dari kaitannya dengan dua konsepnya tentang ruang publik, yaitu sebagai “ruang penampakan” sekaligus “ruang bersama”.
Totalitarianisme dengan klaim kebenaran tunggalnya, melalui ideologi dan pelenyapan “yang lain” melalui rasisme dan imperialisme, jelas-jelas bukan tindakan publik yang menghasilkan “penampakan” (kebenaran bersama) dan yang meletakkan kepentingan di atas meja bundar bersama (ruang bersama), melainkan adalah “tindakan privat” yaitu perbuatan yang berasal dari dunia privat. Totalitarianisme adalah salah satu bentuk paling radikal dari penyumbatan ruang publik oleh ruang privat (bukan sekadar, dan tidak sama dengan, konsep “kolonisasi” Habermasian), penyumbatan “yang politis” oleh “yang sosial”. Sementara, demokrasi liberal adalah semacam bentuk moderatnya karena mengedepankan “kebebasan privat” yang berasal dari hasrat alami dan ekonomis tidak memiliki tautan maknanya dalam “ruang penampakan” yang adalah “ruang bersama”, dan karena itu kebebasan dalam paham demokrasi liberal tidak bersifat publik.
Untuk mengurai hasil pemadatan pemikiran Hannah Arendt tentang manusia politik di atas, pertama-tama saya menyampaikan paling kurang enam tesis utama yang saya temukan dalam pemikirannya:
Pertama, elemen inti kehidupan manusia sebagai “manusia-manusia” (men) dan bukan Manusia (Man) adalah tindakan (dan wicara). Itu berarti bahwa ada dua cara berada yang fundamental bagi manusia dalam kebersamaannya dengan yang lain, yaitu ekspresi dan komunikasi. Hubungan antara tindakan (ekspresi) dan wicara (komunikasi) saling mengandaikan dan saling melengkapi. Jadi, antropologi filosofis Arendt adalah bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang bertindak dan bertutur, ekspresif dan komunikatif.
Kedua, antropologi filosofis ini didasarkan pada asumsi tertentu yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang plural dan bebas. Pluralitas manusia terletak dalam kesamaannya yaitu bahwa mereka tidak sama. Sementara kebebasannya terimplikasi dari hakikatnya sebagai manusia yang bertindak karena bertindak berarti memulai dan mencipta, sementara memulai berarti memilih; itulah kebebasan.
Ketiga, antropologi filosofis ini kemudian ditarik Arendt ke arah antropologi politik, yaitu bahwa manusia adalah makhluk politis sebagai hasil konstruksi tindakan bebas dan sadarnya, bukan sebagai bawaan alami sebagaimana diyakini Aristoteles. Jadi, Arendt berada di antara dua kubu besar dalam teori politik, yaitu antropologi (politik) Aristotelian dan sosiologi politik Hobbesian (1).
Keempat, tindakan (dan wicara) hanya akan terjadi, dan hanya bisa dipahami, dalam masyarakat. Masyarakat yang dipahami Arendt adalah ruang publik sebagai dunia bersama tempat manusia saling berbagi, saling memahami, saling mendengarkan dan melihat. Resiprositas ini terkait dengan hakikat ruang publik (politik) sebagai arena penyingkapan kebenaran melalui relasi kebebasan dalam kepluralan manusia-manusia. Ruang publik adalah ruang antara, ruang yang ada di antara (inter-est), yang mempertautkan pelbagai kepentingan (interest) manusia-manusia yang duduk mengitarinya, saling memandang dan saling mendengarkan.
Kelima, kewarganegaraan menurut Arendt adalah kewarga-ruangpublikan. Sebagai warga ruang publik manusia diakui sebagai manusia sejauh dan selama ia mengekspresikan diri dalam tindakan dan mengkomunikasikan gagasan dan kepentingannya dalam wicara.
Keenam, manusia di luar kelima tesis di atas bukanlah manusia politik melainkan, mungkin, hanya sekadar manusia sosial dan manusia ekonomis. Hannah Arendt sangat membedakan “yang politis” dari “yang sosial”, apalagi dari “yang ekonomis”, dan memandang bahwa hanya “manusia politik”-lah yang manusiawi (human). Hanya “sang Satu” yang mahakuasa, dan politik yang manusiawi bukanlah politik mahakuasa ala totalitarianisme atau ala Leviathan Hobbesian dan ala borjuis Lockean. Dengan demikian, emansipasi manusia adalah penebusannya bukan dari “keterasingan positif” dialektika Hegelian belaka, bukan pula dari “keterasingan negatif” Marxian yang dilihat bersumber pada kapitalisme, bukan pula “keterasingan negatif” religius berupa kejatuhan ke dalam dosa atau kemenduniaan (semisal paham pembebasan dalam Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu). Menurut Arendt, emansipasi manusia hanya terjadi melalui penebusan politik dari “keterasingan eksistensial”, yaitu keterasingan akibat “tindakan eksitensial” di luar cahaya kepublikan.
Tujuan tulisan ini adalah mengungkapkan asumsi manusia politik Arendtian yang menjadi basis konstruksi pemikiran politiknya, atau yang memungkinkan adanya politik.
Lebih jauh, saya tidak hanya menyajikan pemikirannya tetapi juga memberikan apresiasi dan penajaman yang menyebar dalam seluruh uraian dan terutama memberikan kritik serta secara tak terhindarkan membangun konsep politik dan manusia politik menurut saya berdasarkan kritik terhadapnya.
Untuk maksud itu, saya berusaha menalar secara runtut mulai, pertama, dimensi kepolitikan manusia menurut Arendt yang dimungkinkan melalui tindakan, dan tindakan itu adalah aktivitas manusia di ruang publik sekaligus ruang publik dicirikan oleh tindakan manusia. Karakter tindakan manusia, terkait dengan dua karakter ruang publik, sebagai “ruang penampakan” dan “ruang bersama”, yaitu ketakterdugaan sekaligus ketakdiharapkanan dan relasional. Tetapi apa yang memungkinkan bagi tindakan manusia? Jawabannya: kebebasan dan kepluralan manusia.
Untuk itu, pada bagian kedua saya akan menguraikan konsep kebebasan Arendtian sebagai alasan adanya politik dan, bersamaan dengan itu, mengetengahkan argumennya tentang fakta pluralitas manusia-manusia sebagai syarat mencukupi, bukan sekadar syarat perlu, bagi kehidupan politik. Kebebasan dan pluralitas ini bagai dua sisi mata uang yang saling mengandaikan. Namun demikian, karakter ketakterdugaan dan relasional tindakan yang diuraikan pada bagian pertama ternyata, dalam sejarahnya, berimplikasi pada lahirnya politik yang apolitis seperti totalitarianisme dan demokrasi liberal, yang akan saya paparkan pada bagian ketiga tulisan ini.
Selanjutnya, pada bagian keempat, saya akan “memunculkan” konsep “manusia politik” menurut Arendt dengan melihat keterkaitannya dengan konsep Arendt yang memandang politik sebagai semacam “kategori transendental” Kantian, atau sebagai perangkat epistemologis untuk memahami “siapa” manusia. Seluruh konstruksi pemikiran politik Arendt dibangun di atas kritiknya terhadap tradisi filsafat politik Barat sejak Plato, selain didorong oleh pengalamannya secara langsung berhadapan dengan totalitarianisme Nazi, revolusi Hungaria, demokrasi liberal Amerika, dan sebagainya.
Dengan menafsirkan alegori Gua Plato secara politik, Arendt menuduh para filsuf sejak Plato, sebagai apolitis, dan dengan demikian filsafat mereka pun apolitis, karena menyendiri dalam solitudo kontemplatif.
Kritik yang saya sajikan pada bagian penutup ini akan memperlihatkan sebaliknya bahwa, berdasarkan alegori Gua Plato itu, tindakan filsuf “menarik diri”, “mengambil jarak” dari politik, dan “masuk-kembali” ke dalam gua politik, justru sangat politis.
Pada bagian ini juga saya mengetengahkan sebuah solusi lain bagi politik dan manusia politik Arendtian dengan memperkenalkan sebuah ruang lain, melampaui ruang publik dan ruang privat, yaitu “ruang-antara” di mana politik yang sejati berlangsung melalui tindakan manusia-manusia pelalu-lalang ruang-antara itu.
Ruang publik dan kepolitikan tindakan manusia
Konsep kewarganegaraan dan konsep ruang publik Hannah Arendt adalah dua dari tiga konsep penting—yang lainnya lagi, dan bahkan paling penting, adalah “teori tindakan”. Ketiganya saling berhubungan. Membicarakan kewarganegaraan dan ruang publik tanpa mendasarkannya pada teori tindakan, bagi Arendt, adalah tidak mungkin. Karena itu, sebelum masuk ke konsep Arendt tentang kewarganegaraan dan ruang publik, perlu kita cermati dulu teori tindakannya.
Konsep kewarganegaraan didasarkan pada antropologi khas Hannah Arendt yang memandang manusia dalam tiga dimensi vita activa, yaitu kerja (labor), karya (work), dan tindakan (action). Dari ketiganya, yang mengekspresikan dan mendasarkan dimensi politik manusia adalah tindakan. Apa artinya? Politik bukanlah bawaan, dan karena itu niscaya, melainkan buatan, dan karena itu kontingen (2). Politik adalah suatu tindakan sengaja. Tetapi tindakan itu sendiri tidak mungkin tanpa masyarakat. Kalau aktivitas lain (kerja dan karya) dapat dimengerti di luar masyarakat, tindakan tidak. Bahkan, tindakan adalah prerogatif eksklusif manusia.3 Oleh karena itu, tindakanlah yang membedakan manusia dari spesies binatang lainnya, bahkan dari para dewa sekalipun.
Manusia masihlah tetap manusia tanpa kerja dan karya, tetapi tanpa tindakan (dan wicara) manusia bukan lagi manusia (Human Condition, 176). Tindakan berarti memulai, menginisiasi. Tindakan memulai ini adalah ekspresi kebebasan manusia, sebuah kondisi dasar lain, selain pluralitas. Dalam kata-kata Arendt sendiri, “Dengan terciptanya manusia, prinsip permulaan masuk ke dunia, ini hanya cara lain untuk menyatakan bahwa prinsip kebebasan itu tercipta ketika manusia diciptakan, bukan sebelum diciptakan” (Human Condition, 177).
Setuju dengan Aristoteles, Arendt melihat bahwa dari semua aktivitas manusia, yang mendasarkan kehidupan politik adalah tindakan (praxis) dan wicara (speech, lexis). Bahkan Arendt secara lebih jelas melihat bukan hanya hubungan antara tindakan dan wicara, melainkan bahwa keduanya selalu ada bersama (coeval) dan sama (coequal). Namun demikian, wicara itu sendiri sudah merupakan sebuah tindakan (Human Condition, 25-26). Tetapi juga, tindakan tanpa wicara tidak bermakna apa-apa (Human Condition, 180-181). Di sini tersirat posisi Arendt dalam memandang politik sebagai komunikasi (wicara) intersubyektif yang menempatkan kepentingan bersama di atas “meja bundar”, dan kepentingan bersama itu didapatkan dari penyaringan pelbagai kepentingan singular yang “sama” pada setiap agen (karena itu dinamakan “kepentingan bersama”), dan kepentingan singular itu dikenal oleh ruang publik melalui ekspresi atau tindakan dan wicara atau komunikasi.
Tindakan dan wicara menyingkapkan “siapakah” manusia itu, dan bukan sekadar “apakah” manusia itu. Pertanyaan “apakah” manusia adalah pertanyaan esensial dan itu mengandaikan kesamaan total manusia. Itu berarti manusia adalah makhluk tunggal. Sementara, pertanyaan “siapakah” manusia adalah pertanyaan eksistensial dan itu mengandaikan pluralitas manusia. Dengan demikian, kita bisa memahami maksud Arendt dengan mengatakan bahwa tindakan dan wicara menyingkapkan “siapakah” manusia itu (4), karena tindakan dan wicara mengandaikan pluralitas dan kebebasan, sebagai dua kondisi dasar kebersamaan manusia. Kita kutip kata-kata Arendt: “Dalam tindakan dan wicara, manusia memperlihatkan siapa diri mereka, mengungkapkan identitas personal khas mereka dan dengan demikian menampakkan diri mereka di dunia manusia. …..Penyingkapan akan ‘siapakah’ manusia yang berbeda dari ‘apakah’ manusia—kualitasnya, talentanya, baik yang dia hamparkan atau sembunyikan—secara implisit ada dalam setiap tindakan dan wicara manusia” (Human Condition, 179).
Teori tindakan Hannah Arendt sebagaimana dikemukakan di atas sarat dengan dimensi kepublikan. Dengan kata lain, teori tindakan Arendt tidak dapat dipahami di luar konsepnya tentang ruang publik. Arendt mengartikan ruang publik dalam dua pengertian: “ruang penampakan” dan “dunia bersama” (Human Condition, 50-55). Kata Arendt, “penampakan [cetak miring dari penulis], sesuatu yang bisa dilihat dan didengar oleh orang lain seperti juga oleh kita sendiri, menentukan realitas. Dibandingkan dengan realitas yang terlihat dan terdengar, kekuatan terbesar dalam hidup kita yang paling intim— hasrat hati, pemikiran, dan kehendak—mengarah pada eksistensi yang tidak jelas dan berbayang-bayang, kecuali kalau dan sampai semua hal itu ditransformasi, dideprivatisasi dan dideindividualisasi. . .ke dalam bentuk yang sesuai untuk ruang penampakan. . . .Kehadiran orang lain yang melihat apa yang kita lihat dan mendengar apa yang kita dengar meyakinkan kita tentang realitas dunia dan diri kita sendiri…” (Human Condition, 50).
Ruang publik sebagai ruang penampakan juga berarti tempat saya dikenali sebagai manusia oleh yang lain karena saya “berada di antara manusia” (inter homines esse). Ruang publik sebagai ruang penampakan akan memisahkan apa-apa yang tidak relevan dengan kehidupan bersama itu sebagai “masalah privat”, dan karena itu “cahaya kepublikan” itulah yang menyinari apa yang privat, bukan sebaliknya (Human Condition, 51-52).
Ruang publik sebagai “dunia bersama” (common world), dalam arti dunia yang kita pahami bersama, hidupi bersama, adalah dunia “yang sama bagi kita semua, yang berbeda dari tempat pribadi kita di dalamnya” (Human Condition, 52). Dunia tidaklah sama dengan bumi atau alam. Kalau bumi atau alam adalah ruang bagi seluruh makhluk hidup, maka dunia adalah sebuah kategori khas bagi manusia. Dunia menghubungkan dan sekaligus memisahkan manusia pada waktu yang sama.
Ruang publik sebagai dunia bersama adalah ruang “di antara” (in between) yang menyatukan kita bersama dan mencegah kita saling menelikung. Dunia bersama memungkinkan manusia hidup bersama dalam arti bahwa “pada esensinya adalah sebuah dunia yang berada di antara mereka yang memilikinya sebagai milik bersama, sebagaimana halnya sebuah meja yang ditempatkan di antara mereka yang duduk mengitarinya” (Human Condition, 52). Jika meja itu hilang, hilanglah kebersamaan itu.
Lebih lanjut Hannah Arendt mengatakan bahwa ruang publik sebagai dunia bersama adalah “dunia yang kita masuki ketika kita lahir dan dunia yang kita tinggalkan ketika kita mati. Ia melampaui rentang waktu hidup kita di masa lalu atau masa depan; ia sudah ada sebelum kita datang dan akan hidup lebih lama daripada kita. Ia adalah dunia yang kita miliki bersama bukan hanya dengan orang yang hidup hidup bersama kita, melainkan juga dengan orang yang sebelum kita dan dengan orang yang datang sesudah kita. Tetapi dunia bersama bisa hidup lebih lama untuk generasi yang akan datang hanya sejauh ia tampak di publik…[M]anusia memasuki ruang publik karena mereka menginginkan sesuatu yang mereka miliki atau sesuatu yang mereka miliki bersama dengan orang lain untuk melanggengkan kehidupan mereka di bumi ini” (Human Condition, 55)(5).
Dunia bersama ini akan mengalami destruksi paling tidak oleh atau dalam dua hal. Pertama adalah jika terjadi isolasi radikal, ketika orang saling tidak bersetuju satu sama lain. Kasus seperti ini terjadi, misalnya, dalam pemerintahan tiranis, atau dalam masyarakat anarkis. Kedua adalah dalam “masyarakat massa” atau “histeria massa”, di mana kita melihat semua orang tiba-tiba bertingkah seolah-olah mereka adalah anggota sebuah keluarga, masing-masing menggandakan dan melestarikan perspektif orang di sekitarnya. “Dalam kedua kasus ini, manusia telah berubah total menjadi privat, yaitu mereka tidak lagi dapat melihat dan mendengar yang lain, dan tidak lagi dapat didengar dan dilihat yang lain” (Human Condition, 58). Politik menjadi lenyap ketika yang publik berubah menjadi yang privat. Dalam kedua kasus itu politik menjadi lenyap karena kebebasan dan pluralitas telah lenyap. Dalam kasus kedua, pluralitas jelas-jelas telah berubah menjadi ketunggalan. Sementara, dalam kasus pertama pluralitas tetap eksis, malah “dirayakan”, tetapi pluralitas yang tidak lagi dimengerti sebagai pluralitas karena kebebasan telah menjadi chaos. Padahal, pluralitas tidak dapat dimengerti tanpa kebebasan, demikian juga sebaliknya.
Pluralitas dan kebebasan sebagai kondisi kemungkinan bagi politik
Tindakan, kata Arendt, “sebagai satu-satunya aktivitas yang langsung merentang antara manusia tanpa perantaraan apa pun, berkorespondensi dengan pluralitas yang adalah kondisi manusia, yaitu fakta bahwa manusia-manusia (men) dan bukan Manusia (Man) tinggal di bumi dan mendiami dunia. Kalau aspek-aspek lain bisa berhubungan dengan politik, pluralitas adalah kondisi itu sendiri—bukan sekadar conditio sine qua non, melainkan conditio per quam bagi semua kehidupan politik” (Human Condition, 7).
Kalimat terakhir ini memuat poin yang sangat penting dalam pemikiran Arendt, dan karena itu perlu saya perjelas. Pluralitas bukan sekadar conditio sine qua non (syarat yang tidak bisa tidak) secara implisit berarti bahwa pluralitas adalah salah satu dari sekian banyak syarat kemungkinan politik, dan di antara mereka mungkin ada yang bisa dihilangkan, diabaikan, ditiadakan, tetapi yang harus ada adalah pluralitas. Tetapi bagi Arendt, hubungan pluralitas dengan politik tidaklah demikian, melainkan bahwa pluralitas adalah conditio per quam (syarat itu sendiri) yang secara implisit saya tangkap mengandung dua makna yang saling mengandaikan: pertama berarti pluralitas adalah satu-satunya syarat kemungkinan bagi politik; dan kedua, dikatakan sebagai syarat satu-satunya karena fakta antropologis manusia yang memang plural, manusia-manusia (men) 11 dan bukan Manusia (man). Dengan kata lain, dengan memakai bahasa filsafat, pluralitas bukanlah sekadar “syarat perlu”, melainkan “syarat mencukupi” bagi politik, dan itu berarti bahwa cukup dengan pluralitas saja politik menjadi dimungkinkan. Aspek-aspek antropologis lain hanyalah tambahan yang boleh ada boleh tidak.
Selanjutnya, kalau kondisi manusia bagi kerja (labor) adalah “kehidupan itu sendiri”, dan bagi karya (work) adalah “keduniawian” (wordliness) maka kondisi bagi tindakan adalah pluralitas; dan tindakan, tidak dapat tidak, adalah politis. Pluralitas, kata Arendt, “adalah kondisi atau prasyarat bagi tindakan manusia karena kita semua adalah sama, yaitu bahwa, manusia, entah bagaimana sedemikian rupa tidak pernah sama dengan siapa pun yang pernah, sedang, dan akan ada” (Human Condition, 8). Kalimat ini bisa kita katakan dengan kata-kata yang paradoks: kesamaan manusia adalah justru ketidaksamaannya!
Pluralitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi tindakan dan wicara, menjadi tempat berlangsungnya dialektika antara kesamaan/kesetaraan dan kebedaan (Human Condition, 175) (6). Kesamaan menjadi basis bagi adanya pemahaman terhadap satu sama lain dan bagi perencanaan dan “ramalan” akan kebutuhan manusia-manusia masa depan. Kebedaan menjadi basis bagi tindakan dan wicara agar bisa dimengerti. Dalam kata-kata Arendt sendiri, “Jika manusia tidak sama, mereka tidak pernah bisa saling mengerti dan melihat kebutuhan manusia masa depan. [Tetapi] jika manusia tidak berbeda, mereka tidak butuh tindakan dan wicara untuk saling mengerti” (Human Condition, 175-176) (7).
Kita sudah melihat gagasan Arendt bahwa pluralitas adalah conditio per quam bagi politik, dan prasyarat manusia (human condition) bagi tindakan adalah pluralitas. Itu berarti bahwa politik adalah tindakan (juga wicara), juga sebaliknya, bahwa tindakan adalah politis. Tindakan mengimplikasikan kebebasan karena bertindak menurut Arendt berarti memulai, mencipta; dan memulai dan mencipta berarti melakukan pilihan-pilihan (Human Condition, 177). Itulah kebebasan. Tindakan mengimplikasikan kebebasan tidak dibaca sebagai tindakan yang menghasilkan atau mengakibatkan kebebasan tetapi tindakan memprasyaratkan kebebasan. Politik adalah tindakan, dan karena itu politik, tidak bisa tidak, memprasyaratkan kebebasan. Politik tanpa kebebasan bukanlah politik. Kebebasan adalah kondisi kemungkinan bagi politik.
Meskipun konsep kebebasan politik tersebut tidak dieksplorasi begitu mendalam dalam Human Condition, tanpa memahami teori tindakannya dan konsep ruang publik, konsep kebebasannya tidak bisa dimengerti secara utuh. Tetapi, di sana sudah tampak posisi Arendt yang melawankan kebebasan dengan keniscayaan (necessity). Keniscayaan adalah sebuah kategori untuk alam, sementara kebebasan adalah kategori untuk politik. Konsep kebebasan digali secara lebih mendalam dalam dua buku Arendt yang lain: Between Past and Future (1961) dan On Revolution (1963) (8).
Dalam esainya “What Is Freedom” yang termuat dalam Between Past and Future, Arendt mengembangkan konsepnya tentang kebebasan politik sebagai virtue atau keutamaan dan mengkontraskannya dengan kebebasan sebagai “kehendak bebas” (free will). Selain paham kebebasan kehendak yang sudah secara tradisional sangat mendominasi pemahaman kita tentang politik, terdapat juga hal lain yang sama merusaknya, yaitu pemahaman yang keliru dengan menyamakan kebebasan sebagai “independensi” dan kedaulatan (sovereignty atau self-determination).
Menurut Arendt, jika kebebasan dipahami sebagai independensi (ketidaktergantungan) maka akan timbul kesulitan karena politik persis mengandaikan kesalingtergantungan (interdependency). Jika dipahami sebagai independensi, kebebasan berarti kebebasan “dari” politik. Hal ini tentu saja absurd bagi Arendt yang memahami kebebasan dalam konsep antiknya, yaitu kebebasan sebagai konsep politik. Kebebasan eksis hanya di dalam ruang politik yang tidak lain adalah ruang publik. Kebebasan juga bertentangan secara antagonistik secara konseptual dengan kedaulatan: “Kebebasan dan kedaulatan tidaklah sama dan keduanya bahkan tidak dapat eksis secara simultan” (Between Past and Future, 14).
Dikaitkan dengan konsep vita activa-nya, independensi dan kedaulatan adalah dua konsep yang masuk dalam kategori karya (work), dan bukan kategori tindakan. Karena itu keduanya tidak politis. Menurut Arendt, kedaulatan (self-determination) adalah nama lain dari kehendak bebas (free will). Melihat kebebasan sebagai kehendak bebas akan membuat kita memahami politik sebagai arena peperangan. Mengapa?
Karena hal itu akan “mengarah pada penolakan kebebasan di satu sisi atau mengarah pada pemahaman bahwa kebebasan dari satu orang, atau dari sebuah kelompok, atau suatu badan politik bisa dibeli hanya dengan mengorbankan kebebasan itu sendiri” (Between Past and Future, ibid).
Karena itu, Arendt berkeyakinan bahwa “jika manusia-manusia ingin bebas, persis kedaulatanlah yang harus mereka singkirkan” (Between Past and Future, 165). Kata Arendt, “Tindakan, untuk menjadi bebas, harus bebas dari motif di satu sisi, dari tujuan yang disasar sebagai hasil yang dapat diperkirakan di sisi lain. Ini tidak untuk mengatakan bahwa motif dan sasaran bukanlah faktor yang penting dalam setiap tindakan apa pun, tetapi. . .tindakan itu bebas sejauh ia mampu mentrasendensi keduanya” (Between Past and Future, 151). Dengan ini Arendt mau mengatakan konsep kebebasan politik sebagai sesuatu yang berlawanan dengan rasio instrumental dalam karya (work). Kebebasan yang dimaksudkan Arendt di sini tidak dipahami dalam hal ada atau tidak adanya prasyarat tertentu melainkan lebih dalam hal relasi sang aktor dengan motifnya sendiri, yaitu dirinya sendiri.
Dalam “What Is Freedom” Hannah Arendt menjelaskan konsep kebebasan yang adalah inheren dalam tindakan politik dengan memetik kembali konsep “virtu” (Italia) dari Machiavelli. Menurutnya, keutamaan adalah “kehebatan (excellence) yang dengannya manusia memanfaatkan peluang yang dihamparkan oleh dunia kepadanya dalam kedok keberuntungan (Between Past and Future, 153) (9). Di sini ada tiga karateristik; dalam kaitan dengan relasi seseorang dengan yang lain: virtue adalah sejenis “keahlian atau kemampuan tingkat tinggi” (virtuosity), yaitu suatu “kehebatan” (excellence); audiens sebagai “ruang kebebasan bisa muncul”; dan “keberanian” (courage) (Between Past and Future, 153-154, 156).
Menurut Arendt, keberanian adalah politis sejauh seseorang tidak dijajah oleh kepentingan pribadi semata melainkan selalu terarah pada kepentingan publik. “Keberanian tidak dapat diabaikan karena dalam politik bukanlah hidup melainkan dunialah yang dipertaruhkan” (Between Past and Future, 155-156). Hal ini memprasyaratkan suatu kemampuan mengarahkan perhatian seseorang pada kepentingan publik dan mengesampingkan kepentingan sendiri bahkan dengan mempertaruhkan hidup. Penampakan kebebasan terjadi bersamaan dengan tindakan yang berlangsung. Manusia-manusia, tandas Hannah Arendt, adalah bebas sejauh mereka bertindak, bukan sebelum juga bukan setelah, karena “bebas dan bertindak adalah sama” (Between Past and Future, 152 dan seterusnya).
Dalam On Revolution, Hannah Arendt membedakan kebebasan politik (political freedom) dari kebebasan personal (personal freedom) (10). Bagi Arendt, kebebasan politik adalah kebebasan warisan pemikir seperti Aristoteles dan praktik polis di Yunani kuno, itulah yang sebenarnya dinamakan kebebasan. Kebebasan jenis ini, sekarang ini, dipahami sebagai kebebasan positif (positive liberty), yaitu kebebasan untuk (freedom to) melakukan apa pun dan menjadi apa pun berdasarkan otonomi seseorang. Sementara, kebebasan personal adalah, dalam kaca mata Arendt, kebebasan yang dipahami dalam politik modern (liberty of the moderns). Kebebasan demikian berada di luar politik.
Dalam paham sekarang ini, kebebasan itu dinamakan sebagai kebebasan negatif (negative freedom), yaitu kebebasan dari (freedom from) apa pun dan siapa pun yang menjadi penghalang bagi pemenuhan sesuatu atau pemenuhan diri. Tetapi, sebenarnya Arendt tidak memakai konsep positif dan negatif, melainkan politik dan personal, dan konsep itu melampaui konsep kebebasan positif dan negatif, yang bahkan sangat kental mewarnai pertentangan antara liberalisme dan sosialisme, yang kemudian juga tercermin dalam hak asasi manusia. Kategori kebebasan dikaitkan dengan rakyat bukan sebagai manusia melainkan sebagai warga negara atau warga polis.
Kebebasan, kata Arendt, dipahami sebagai sesuatu yang manifes secara khusus, melalui kegiatan manusia. Kegiatan-kegiatan itu bisa muncul dan menjadi nyata hanya ketika orang-orang lain melihatnya, menilainya, dan mengenangnya. Hidup sang manusia bebas memerlukan kehadiran orang lain. Kebebasan itu sendiri membutuhkan sebuah tempat orangorang bisa datang bersama, yaitu agora, arena pasar, atau polis, arena ruang politik (On Revolution, 31).
Dengan demikian, kebebasan yang dipahami Arendt memang lebih dalam pengertian sebagai kebebasan politik. Dengan kata lain, dapat saya tekankan maksud Arendt adalah kebebasan di luar kategori kebebasan politik sama sekali tidak bisa dimengerti, persis karena status ontologis politik memiliki status antropologis juga, di mana tanpa politik manusia bukan lagi manusia. Kebebasan sebagai “kebebasan politik” dikaitkan dengan agora di negara kota Yunani, ruang politik. Interpretasi politik Yunani kuno yang asli terhadap kebebasan dan praktik politik kuno terhadap demokrasi kemudian dilencengkan oleh fakta pemikiran Plato dan Aristoteles serta para murid mereka “menyingkir” dari pusat kehidupan publik negara kota, dari agora, dan dari kehidupan politik itu sendiri. Pandangan mereka didiskusikan dan disebarkan hanya dalam lingkup kecil. Kebebasan sebagai warga negara kemudian hanya dibatasi dalam paham sebagai kebebasan dalam hal pertikaian ilmiah. Menurut Arendt, pengalaman akan kematian Socrates (dalam kasus Plato) dan pelarian Aristoteles setelah kematian Alexander Agung, menjadi faktor penting “pelarian” para filsuf ini dari kehidupan politik riil. Perilaku antipolitik mereka berdampak pada devaluasi hakikat politik dan kebebasan politik. Introversi atau kemenyendirian, isolasi dari ruang publik berlawanan secara diametral dengan praktik negara-kota Yunani kuno, karena ruang privat adalah ruang sang manusia tunggal (sphere of Man) dan bukan ruang gaul manusia-manusia atau rakyat.
Konsep (filsafat) politik modern pun tidak lebih bagus dari pemahaman politik tradisional sejak Plato, yang antara lain tergambar dalam filsafat politik Thomas Hobbes dan para pemikir “teori kontrak sosial” lainnya (12). Kebebasan kemudian dipahami sebagai keamanan diri dan keamanan sosial (individual and social security). Implikasinya adalah bahwa politik, atas nama kebebasan yang dipahami sebagai keamanan itu, hanya bisa tegak dengan sebuah pemerintahan atau rezim Leviathan, rezim totaliter (Between Past and Future, 143-171). Bagi Hannah Arendt, politik adalah suatu kekhususan dan kekhasan kondisi manusia, sebuah institusi buatan-manusia, sebuah ruang kehidupan bersama yang bebas. Politik menciptakan dan menjamin kebebasan (kebebasan politik) dan keberanian (courage) sebagai suatu keutamaan/kehebatan. Politik menjamin adanya upaya memulai secara terus-menerus, dan mengizinkan kita menghayati pengalaman akan suatu minat yang sangat dalam. Politik adalah perlawanan tak kunjung henti terhadap rezim totaliter dan bisa, bahkan harus, menjadi alternatif bagi suatu masyarakat konsumeristik dan masyarakat totalisasi pasar.
Konsep kebebasan politik Arendt berada dalam tradisi yang dipercayainya yaitu tradisi republikan klasik. Tradisi ini memandang kebebasan sebagai sesuatu yang selalu bersifat publik, dimiliki dan dinikmati oleh para warga yang merawat res publica mereka sendiri. Meskipun ia menyajikan penyelidikannya sebagai upaya memulihkan dan mengartikulasikan pengalaman-pengalaman masa lalu (Between Past and Future, 148, 154, 166), pemahamannnya tentang kebebasan pada dasarnya memiliki elemen modern yang khas, yaitu pengaruh eksistensialisme atau Kantianisme dalam hal spontanitas (13). Pendekatannya yang distingtif terhadap kebebasan muncul dari perpaduan kedua tradisi filsafat modern tersebut, yang dikaitkan dengan pemahamannya yang sangat jernih terhadap filsafat politik antik. Dari eksistensialisme ia menarik inspirasi akan masa depan yang terbuka bagi setiap individu, yang kemudian dicangkokkannya kepada konsep republikan klasik di mana para warga berdiri bahu-membahu mempertahankan kebebasan bersama mereka.
Namun demikian, jika spontanitas individual adalah akar dari kebebasan, mengapa politik diperlukan sebagai wilayah di mana kebebasan berumah? Jawaban Arendt, sebagaimana ditelaah Canovan, kembali mengacu kepada pluralitas manusia. Pluralitas berarti bahwa ketika seorang individu ingin melakukan sesuatu, ia memerlukan kerja sama dengan yang lain. Kebebasan politik adalah “sebuah kualitas ‘saya-bisa’ (I-can) dan bukan ‘saya-akan’ (I-will)” (Hannah Arendt, A Reinterpretation, 213). Kebebasan (kebebasan politik) hanya ada sejauh ada perbuatan nyata, suatu tindakan yang membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Inilah yang disebut inisiasi, dan inisiasi adalah kualitas khas manusia. Dan untuk membuat sesuatu yang belum ada itu menjadi ada, diperlukan kerja sama dengan yang lain, yang memberikan mereka kekuasaan (power) dan bukan dengan kekerasan (violence) untuk melangsungkan kerja sama itu. Dalam kerja sama itulah kapasitas individual manusia akan spontanitasnya menjadi satu tubuh dalam kebebasan yang manifes secara penuh.
Orisinalitas konsep kebebasan politik Arendt terutama terletak dalam pandangannya tentang pluralitas manusia sebagai bukan hanya conditio sine qua non melainkan conditio per quam dari tindakan manusia. Kalau “kebebasan adalah raison d’être politik”, sementara “kebebasan adalah tindakan itu sendiri”, dan kalau “conditio sine qua non dan conditio per quam dari tindakan adalah pluralitasnya” maka politik adalah tindakan, politik adalah kebebasan, dan kebebasan tidak dapat tidak ada karena fakta pluralitas manusia. Tetapi, sebagaimana sudah saya kemukakan di atas bahwa ruang bersama yang adalah ruang manifestasi kebebasan manusia itu mengalami destruksi oleh hasrat ketunggalan di satu sisi dan hasrat kaotis (sebagai varian kebebasan yang dipahami sebagai relasi hak yang saling bertempur).
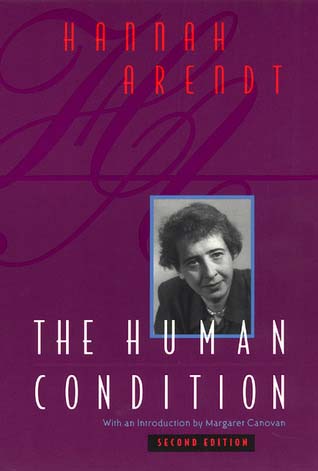
Memanusiawikan kekuasaan: melawan totalitarianisme dan demokrasi liberal (14)
Totalitarianisme dan demokrasi liberal, dalam pandangan Arendt, memiliki kesamaan dalam hal kekuasaan yang tidak manusiawi. Ketidakmanusiawian kekuasaan dalam totalitarianisme terletak dalam klaim ideologisnya yang seolah “ilahi”, yang rezimnya mahakuasa dalam hal kekuasaan, dan tunggal dalam hal kebenaran. Itu bertentangan dengan manusia politik yang hanya dapat menemukan makna eksistensialnya dalam kebebasan dan pluralitas. Sementara, ketidakmanusiawian kekuasaan dalam demokrasi liberal harus dijelaskan dengan sedikit bertahap.
Klaim kebebasan dalam demokrasi liberal adalah kebebasan privat, bukan kebebasan politik, yang lebih mengekspresikan kesosialan manusia ketimbang kepolitikannya, yang lebih mengedepankan karakter kerja dan karya dan bukan tindakan. Sebagai kebebasan privat, maka demokrasi liberal hanya mengedepankan relasi hak atas kebebasan untuk kepentingan diri, bukan relasi kebebasan untuk mewujudkan haknya dalam kebersamaan di ruang publik. Sementara, sebagaimana telah dijelaskan di atas, manusia hanyalah manusia dalam pengertian yang utuh sejauh ia politis. Dengan kata lain, manusia adalah manusiawi sejauh ia politis. Kekuasaan dalam demokrasi liberal tidak politis karena ia bukan berasal dari ruang publik, melainkan ruang privat. Karena itu, kekuasaan dalam demokrasi liberal tidak manusiawi dalam arti bahwa ia tidak menunjang upaya sadar manusia untuk menemukan puncak eksistensinya menjadi “manusia politik”.
Arendt, sebagaimana dibahasaulangkan oleh Conovan (The Cambridge Companion to Hannah Arendt, 27), dan sebagaimana telah disinggung pada bagian pengantar di atas, melihat bahwa totalitarianisme mengilustrasikan kapasitas manusia untuk memulai (yang adalah karakter fundamendal tindakan dan kebebasan), di mana kekuatan berpikir dan bertindak menemukan bentuknya yang baru, kontingen, dan tak-terduga. Inilah yang kerap disebut sebagai paradoks dalam tindakan manusia. Tindakan manusia memang selalu mengandung dimensi ketakterdugaan dan ketakdiharapkanan yang berangkat dari keyakinan manusia modern bahwa “segala sesuatu adalah mungkin” (The Origins of Totalitarianism, 459), tetapi dimensi destruktif tindakan manusia yang muncul dalam totalitarianisme berakar pada “kecurigaan yang sangat mengakar dalam diri manusia modern atas segala sesuatu yang tidak diperbuatnya sendiri.” (15)
Mari kita lihat secara cermat paradoks modernitas ini. Di satu sisi manusia sadar akan ketakterdugaan tindakannya, tetapi di sisi lain ia tidak mau ketakterdugaan itu tanpa kontrol. Karena ketakterdugaan itu sangat tak terpikirkan, upaya kontrol terhadapnya tidak dapat dilakukan selain hanya dengan kekuasaan total. Dengan demikian, kekuasaan total dalam rezim totalitarianisme itu, jika ingin mahakuasa, harus “membunuh” tindakan melalui teror total dan “membunuh” pemikiran melalui ideologi total. Itu berarti, supaya mahakuasa, rezim totalitarianisme harus melucuti manusia menjadi “manusia yang sama dengan binatang” (animal-species man) (The Origins of Totalitarianism, 457) (16). Dengan demikian, totalitarianisme mengubah “iman” modernisme bahwa “segala sesuatu adalah mungkin” menjadi “segala sesuatu dapat dihancurkan” (The Origins of Totalitarianism, 459).
Menurut Arendt, bukan hanya totalitarianisme yang “membunuh” pemikiran, tindakan dan wicara, tiga fakultas fundamental dalam diri manusia politik, melainkan juga demokrasi liberal. Tentang tindakan dan wicara telah banyak disinggung di atas. Menurut Arendt, pemikiran adalah semacam dialog atau percakapan antara “daku” (me) dan “diriku” (myself), dan konsep seperti ini telah menjadi sesuatu yang penting sejak Plato (Human Condition, 76). Percakapan antara “daku” dan “diriku” ini unik karena pada dasarnya kedua belah pihak berkomunikasi dari posisi yang sama dengan pemahaman bersama (shared understanding). Dengan mengutip Thomas Aquinas, Arendt menegaskan bahwa “kebenaran dapat menyingkapkan dirinya sendiri dalam keheningan sempurna manusia” (Human Condition, 15).
Arendt sangat membedakan antara pemikiran (thought) dari pengetahuan (knowing). Pemikiran melibatkan refleksi kritis personal, sementara pengetahuan tergantung pada keberterimaan kebenaran sebagai sesuatu yang eksternal terhadap persepsi individual (Human Condition, 76-77). Dengan kata lain, Arendt melihat bahwa kebenaran dalam pemikiran berasal dari dalam diri yang reflektif atau kontemplatif, sementara kebenaran dalam pengetahuan berasal dari luar, yang sarat dengan pemaksaan dan koersi. Gambaran perbedaan ini tampak dalam penilaiannya terhadap Eichmann, yang menurut Arendt, ia “benar-benar…tidak menyadari apa yang dia lakukan.” (17).
Ruang publik, menurut Arendt, sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah ruang politik yang menjadi arena penyingkapan kebenaran. Itu berarti, ruang publik, dalam kajian fenomenologis Arendt, adalah ruang untuk berpikir, bertindak dan berbicara untuk sampai pada penyingkapan kebenaran tentang eksistensi manusia sebagai manusia politik. Eichmann jelas gambaran manusia apolitik, yang hanya memiliki pengetahuan (dengan menerima begitu saja kebenaran ideologis di bawah totalitarianisme Nazi) dan tidak berpikir.
Arendt menekankan bahwa wicara adalah manifestasi publik dari pemikiran sejauh “apa pun yang manusia perbuat atau ketahui atau alami hanya masuk akal sejauh hal itu dapat diwicarakan” (Human Condition, 4). Menurut Arendt, pemikiran dalam segala tingkatannya memanifestasikan dirinya dalam dunia melalui wicara dan tindakan. Lalu di mana letak kritik Arendt terhadap demokrasi liberal dalam arti bahwa demokrasi liberal bukanlah ruang tempat manusia bisa berpikir, bertindak dan berbicara sebagai manusia politik?
Problem ini digambarkan oleh Seyla Benhabib sebagai “penyumbatan ‘yang politis’ oleh ‘yang sosial’ dan perubahan ruang publik menjadi ruang palsu (pseudospace) interaksi antarmanusia ketika individu tidak lagi ‘bertindak’ (act) melainkan ‘melulu berperilaku’ (behave) sebagai produsen dan konsumen ekonomi, dan gerombolan penghuni kota.”(18). Pembacaan secara cermat terhadap Human Condition membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan “yang sosial” oleh Arendt adalah animal laborans dengan aktivitasnya berupa “kerja” (labor) yang bekarakter rasio natural dan homo faber dengan aktivitasnya berupa “karya” (work) yang berkarakter rasio instrumentalis. Menurut Arendt, animal laborans tidak mampu memanifestasikan wicara dan tindakan, sementara homo faber adalah manusia yang memiliki pengetahuan tetapi tidak berpikir, dan itulah manusia banal.
Namun harus dicermati bahwa animal laborans dan homo faber bukannya tidak dapat berpikir, melainkan mereka tidak terdorong berpikir (Assessing the Capacities of Democracy, 38). Arena animal laborans dan homo faber tidak memungkinkan untuk berpikir (dan karena itu tidak berkontribusi pada tindakan dan wicara) karena masing-masing rasionalitas natural yang bersifat niscaya dan rasionalitas instrumentalis yang justifikasinya terletak pada tujuan, nilai guna dan kesesuaiannya dengan tujuan yang telah ditetapkan itu (Human Condition, 153).
Upaya penebusan manusia politik oleh Hannah Arendt tidak dengan seruan moralis tetapi dengan melakukan kajian fenomenologis dan menggelar di hadapan kita bahwa manusia memiliki fakultas yang mengakar dalam dirinya yaitu berpikir, bertindak dan berwicara. Ia tidak berseru supaya manusia berpikir agar tidak banal karena hal itu sudah ada dalam diri manusia. Tugasnya hanya menunjukkan kapasitas itu. Namun demikian, seluruh bangunan filsafat Arendt rupa-rupanya “tidak memberi izin” bagi manusia untuk tidak berpikir, sehebat apa pun upaya “penyumbatan” oleh rasio natural maupun rasio instrumentalis terhadap dimensi kepolitikan manusia, persis karena “’hakikat’ manusia hanya ‘manusiawi’ sejauh ia membukakan kemungkinan bagi manusia untuk menjadi sesuatu yang jauh melampaui yang tidak natural, yaitu, menjadi seorang manusia” (The Origins of Totalitarianism, 455). Jadi, meskipun politik bukanlah sebuah keniscayaan Aristotelian maupun sebuah konstruksi instrumentalis Hobbesian dan Lockean, melainkan sebuah konstruksi tindakan bebas manusia yang rasional dalam pluralitasnya, namun hasrat “menjadi” dengan melampaui “yang natural” adalah natural dalam diri manusia. Singkatnya, demokrasi liberal adalah politik yang apolitis karena manusia-manusia yang menghuni ruang politik demokrasi liberal itu telah mereduksi diri, dan direduksi, kembali menjadi manusia-natural dengan rasio keniscayaan dan instrumental, sementara manusia politik adalah manusia-yangmelampaui-yang-natural, atau dengan kata lain dengan ungkapan paradoks, “naturalitas” manusia politik adalah pelampauan-akannaturalitas-nya. Tindakan pelampauan inilah yang akan menyingkapkan “siapa”-nya manusia, bukan “apa”-nya (dalam rasio keniscayaan dan rasio instrumental). Bagian berikut akan saya gunakan untuk menunjukkan ke-“siapa”-an manusia politis dalam konsepsi Arendt.
Manusia politik dan politik sebagai kondisi kemungkinan bagi penyingkapan “siapakah” manusia
Sekarang mari kita perjelas konsep “manusia politik” menurut Arendt dengan memulainya dari perseteruan antik antara filsafat dan politik. Bukan Arendt yang mengatakan perseteruan itu, melainkan ia mengangkatnya kembali dari data historis untuk memperlihatkan posisinya. Arendt menuduh bahwa “filsafat politik” hanyalah “anak tiri” filsafat, dan filsafat yang dimaksudkannya adalah filsafat tradisional Barat sejak Plato atau pasca-Socrates. Menurut Arendt, para filsuf sejak Plato–dengan pengecualian para filsuf eksistensialis terutama Sartre dan Camus, yang menurut hemat saya jejak-jejak itu sangat kental dalam “filsafat” politik Arendt–membangun penjara soliter filosofis dan meninggalkan pergulatan solider eksistensial atas nama “kebahagiaan” dan “kebenaran sejati”. Arendt melacak jejak itu, misalnya, pada Plato dari dua hal yaitu epistemologi atau filsafat pengetahuan (19) dan filsafat politik Plato.
Kita sudah sangat akrab dengan epistemologi atau filsafat pengetahuan Plato dengan alegori Gua. Interpretasi Arendt terhadap alegori yang kerap disebut “Gua Plato” adalah bahwa filsuf harus meninggalkan gua, harus meninggalkan sesamanya, untuk mencapai apa yang “superior”. Gua Plato mewakili kehidupan harian yang biasa di tengah dunia ini dan sang filsuf dianjurkan melarikan diri dari kehidupan demikian untuk menggapai kemampuan tertingginya–yaitu kontemplasi—dalam keheningan menyendiri, dan hanya kembali untuk memberitakan kepada massa yang tidak berpencerahan (sesamanya yang ditinggalkan di Gua). Di sini Arendt mengkritik Plato yang, menurutnya, telah mereduksi kehidupan bersama manusia di sebuah dunia-bersama sebagai “kegelapan, kebingungan dan kepalsuan” dan menganjurkan “siapa pun yang rindu akan kebenaran sejati supaya meninggalkannya jika mereka ingin menemukan langit yang cerah dan penuh ide-ide keabadian” (Between Past and Future, 17). Arendt menemukan “kebingungan” Plato yang memilih menggambarkan para penghuni Gua sebagai orang-orang yang “membeku, terbelenggu di depan sebuah tembok, tanpa kemungkinan apa pun untuk melakukan apa pun atau berkomunikasi satu sama lain.” (20). Melalui contoh alegori Gua Plato ini Arendt mengerti akan dikotomi antara “melihat kebenaran dalam kemenyendirian dan keberjarakan yang jauh dan kebenaran yang tertangkap dalam relasi dan kerelatifan pergumulan manusia” (Between Past and Future, 115), yang pertama menjadi “otoritatif” bagi filsafat politik dalam tradisi Barat. Dibaca secara politik, filsafat pengetahuan Plato jelas sebuah eskapisme dari hingar-bingar kehidupan manusia, dari universalitas ke singularitas, dari ketakkekalan kepada ketakmatian, dan dari kehidupan kepada kematian. Arendt menegaskan klausa terakhir dengan mengambil inspirasi dari konsep Yunani Kuno dan Romawi Kuno bahwa, “hidup” adalah sinonim dari “berada bersama manusia yang lain” (inter homines esse), dan “mati” sinonim dengan “berhenti berada bersama manusia yang lain” (inter homines esse desinere) (Human Condition, 7-8) (21). Dari analisis ini, saya tegaskan karakter pertama manusia politik yang dimaksud Arendt yaitu sebagai manusia-yang-berada-di-dunia sekaligus berada-bersama-yang-lain. Dan berada bersama yang lain berarti berelasi dalam fakta bahwa mereka semua sama dalam hal kebedaannya satu sama lain. Dengan kata lain, relasi dalam “berada bersama yang lain” hanya mungkin terjadi karena pluralitas mereka sekaligus kesetaraannya. Selanjutnya, relasi itu tampak dalam wicara dan tindakan, serta pemikiran. Tanpa pluralitas tak ada kebebasan, tanpa kebebasan relasi tidak ada, dan tanpa relasi tidak ada wicara dan tindakan (dan pemikiran), sementara ketiga hal terakhir ini adalah unsur konstitutif kepolitikan manusia, dan kepolitikan manusia adalah kondisi kemungkinan bagi penyingkapan kebenaran. Di sini tampak jelas jejak-jejak filsafat gurunya Martin Heidegger tetapi sekaligus berbeda karena, tidak seperti Heidegger yang memahami keberadaan manusia di dunia ini sebagai “keterlemparan”, ia memahami dunia sebagai kondisi kepolitikan manusia; dengan kata lain, berbeda dari bumi sebagai kondisi biologis manusia (kerja) dan kondisi sosial manusia (karya), dunialah yang memungkinkan terjadinya politik. Dengan kata lain, politik bukanlah sebuah “keterpaksaan” (akibat “keterlemparan” Heideggerian), juga bukan sebuah “keniscayaan natural” Aristotelian, melainkan sebuah, dapat saya katakan, cara berada di dunia. Menurut saya, dua sisi dari satu koin karater pertama Manusia Politik ini secara tidak langsung menegaskan keyakinan Arendt yang memandang politik sebagai sesuatu yang sekuler (dengan kata lain, politik sebaik apa pun di bawah kepak sayap religius sama sekali bukan politik) sekaligus bahwa politik adalah soal solidaritas (bukan soliter) dengan keterlibatan dan partisipasi nyata melalui tindakan dan wicara.
Filsafat pengetahuan Plato dengan alegori Gua ini tidak terlepas dari pengalamannya menyaksikan kematian Socrates, gurunya, yang melahirkan filsafat politik yang sama juga eskapisme dari politik itu sendiri, tetapi dengan cara yang tidak autentik dengan menyuntikkan ide Raja-Filsuf agar tidak tampak antipolitik. Dengan kata lain, filsafat politik Plato sama sekali bukan filsafat tentang politik, melainkan filsafat untuk politik. Klausa ini bukan dari Arendt, melainkan dari saya, untuk lebih mempertegas apa yang dikritik Arendt pada dan sejak Plato: “apolitisisme para filsuf yang semakin membiak semenjak kematian Socrates” (Between Past and Future, 72). Arendt menegaskan bahwa keengganan yang sangat kental dari kebanyakan filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles terlibat dalam politik riil disebabkan oleh ketakutan dan ketidaksukaan mereka yang sangat mendalam terhadap bagaimana polis Yunani secara simbolis memperlakukan filsafat dalam pengadilan dan kematian Socrates. Plato secara langsung menyaksikan apa yang “massa” (demokrasi) mampu lakukan secara politik, sementara Aristoteles juga mengalami ancaman politik, yang membuatnya membela pelariannya dari Athena setelah kematian Alexander Agung dengan kata-kata, “supaya warga Athena tidak berdosa dua kali terhadap filsafat” (The Hidden Philosophy of Hannah Arendt, 11). Dengan melihat rupa dunia politik itu sebenarnya, tanpa kontrol yang ketat dari filsafat, Arendt yakin bahwa filsafat Platonik dan Aristotelian memulai sebuah tradisi yang memposisikan dan melegitimasi tindakan politik sematamata dan “harus ditentukan oleh filsafat” (inilah yang saya maksud di atas sebagai “filsafat untuk politik”). Young-Bruehl dalam biografinya tentang Arendt cukup tegas mendeskripsikan pandangan Arendt bahwa “para filsuf Barat, sejak pengadilan dan kematian Socrates hingga abad kesembilan belas, lebih memusatkan perhatian pada bagaimana filsafat dapat berlangsung dengan gangguan yang sesedikit mungkin dari hingarbingar politik. Tentu saja Arendt mengakui bahwa dalam tradisi tersebut tak satu pun pemikir besar yang tidak memberikan perhatiannya pada politik, tetapi perhatian itu sama sekali tidak mencerminkan sebuah keyakinan bahwa politik adalah sebuah wilayah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sejati muncul. Ranah politik adalah suatu bidang yang harus diatur sesuai dengan resep-resep yang muncul dari dan di tempat lain dan yang lebih mungkin terdapat pada suatu jenis kebijaksanaan ‘yang lebih tinggi’ ketimbang kebijaksaan praktis.” (22).
Pertentangan antara filsuf (termasuk filsafat) dan politik ini sebenarnya mencerminkan kekeliruan dalam mempertentangkan antara pemikiran (vita contemplativa) dan tindakan (vita activa), di mana para filsuf melihat bahwa politik harus mencerminkan kebenaran dalam vita contemplativa di satu sisi dan bahwa politik itu sendiri tidak memiliki kebenaran dari dalam dirinya sendiri di sisi lain. Untuk itu, politik harus dipandu oleh penguasa vita contemplativa berupa Raja-Filsuf. Lagi-lagi, inilah yang saya katakan sebagai “filsafat untuk politik”, yaitu pemikiran filsuf yang mengidealkan politik tertentu demi keamanan mereka sendiri, dan karena itu filsafat untuk politik sebenarnya dimaksudkan sebagai “politik untuk filsafat (juga, dengan sendirinya, filsuf)”. Dalam kata-kata Arendt sendiri, tujuannya adalah “tidak lebih daripada untuk memungkinkannya bagi dan menyesuaikannya dengan cara hidup sang filsuf” (Human Condition, 14). Dalam The Republic, Plato menggambarkan secara rinci sebuah cetak biru politik yang mendapatkan stabilitasnya serta alasan-adanya Raja-Filsuf yang memerintah secara paternalistik atas massanya. Implikasinya adalah massa tidak memiliki kapabilitas atas tindakan politik di antara mereka sendiri, sebaliknya mereka menjadi semata-mata wayang yang menjalankan aturan dan dengan demikian tidak menjadi partisipan yang aktif dalam politik (The Hidden Philosophy of Hannah Arendt, 12). Atau dalam kata-kata Arendt sendiri bahwa “Plato secara jelas menulis The Republic untuk membenarkan gagasannya bahwa para filsuf harus menjadi raja, bukan karena mereka senang dengan politik, melainkan karena, pertama-tama, dengan begitu mereka tidak akan diperintah oleh orang-orang yang lebih buruk daripada mereka sendiri dan, kedua, hal itu akan menciptakan keheningan yang penuh dan kedamaian yang absolut yang membentuk kondisi yang paling baik bagi kehidupan sang filsuf.” (23).
Dari kritik Arendt terhadap oposisi yang dibangun para filsuf antara filsafat dan politik ini, saya merefleksikan karakter kedua Manusia Politik Arendtian yaitu ia bukanlah sekadar manusia yang berpikir tentang politik, apalagi manusia yang berpikir untuk politik dalam arti bahwa sang filsuf “memaksakan” idenya dalam politik tetapi demi kebahagiaan, kebaikan dan “tirani kebenaran” yang diyakininya sendiri, melainkan bahwa ia adalah manusia yang berpikir dengan berpolitik; sebuah “filsafat dengan berpolitik”. Dengan kata lain, Manusia Politik adalah manusia yang di satu sisi ada kesalingsesuaian antara kontemplasi (pemikiran) dan praksis (tindakan dan wicara) dan di sisi lain kesesuaian itu terjadi karena pemikirannya lahir dari pergumulan politiknya yang riil. Pada dimensi pertama keputusan Socrates untuk “patuh” pada hukum Athena adalah contoh kesukaan Arendt, dan di sisi lain pemikirannya sendiri yang lahir dari pergulatannya dengan pengalaman totalitarianisme serta demokrasi liberal Amerika adalah contohnya.
Selain menunjukkan wicara itu sendiri sudah menjadi sebuah tindakan, di sini kita melihat satu hal lagi bahwa pemikiran itu sendiri (yang terkomunikasikan dalam wicara-tulisan dan, dalam kasus Socrates, wicara-lisan) adalah sebuah tindakan politik. Sebagai tindakan politik, pemikiran (politik) tidak dapat tidak bergulat dalam politik dan menyingkapkan kebenaran melalui dan di dalam politik itu sendiri, bukan melalui dan dari sumber lain di luar politik. Politik itu sendiri sudah merupakan sebuah ruang penampakan kebenaran. Saya berpendapat bahwa politik, yang diyakini Arendt, sebagai ruang publik adalah semacam kategori transendental Kantian di mana kebenaran tentang “siapa” manusia dapat dimengerti atau tersingkap. Dalam kerangka inilah mengapa pada bagian pendahuluan telah saya tegaskan bahwa filsafat politik Hannah Arendt dapat dibaca sebagai sebuah filsafat tentang manusia, dan manusia yang dibicarakannya adalah Manusia Politik.
Sudah dikatakan Arendt bahwa aktivitas manusia yang ketiga, yaitu tindakan, memiliki kaitan erat dengan pluralitas manusia dan bahwa tindakan adalah “aktivitas politis par excellence” (Human Condition, 7-9). (24) Dengan kata lain, tindakan itu bermakna politis dan bahwa politik terkait dengan fakta kemajemukan manusia. Menurut Arendt, “dalam tindakan dan wicara, manusia-manusia memperlihatkan siapa mereka, mengungkapkan secara aktif keunikan indentitas personal mereka”, dan “pengungkapan melalui wicara dan tindakan terjadi di forum di mana orang-orang ada bersama dengan yang lain” (Human Condition, 179-180). Jadi, tindakan itu politis karena bertindak berarti berdiri di hadapan yang lain, berarti untuk dilihat dan untuk berbincang-bincang. Menurut Arendt, identitas sang aktor yang bertindak bukan merupakan sesuatu yang “sudah ada sebelumnya” (pre-existent) yang kemudian dikomunikasikan kepada manusia lain melalui tindakan politik, melainkan bahwa tindakan politik adalah satu-satunya cara sang aktor menemukan dirinya sendiri dan keunikannya (“Hannah Arendt”, 6- 7). Seorang penafsir yang sangat bersimpatik kepada Arendt, Adriana Cavarero membahasaulangkan politik Arendtian sebagai “sebuah ruang relasional […] yang terbuka ketika para aktor yang unik itu mengkomunikasikan diri mereka sendiri satu sama lain secara resiprokal dengan wicara dan tindakan” dan “karakter politik intrinsik wicara tidak terkandung dalam fungsinya yang mengekspresikan apa yang baik, benar, bermanfaat dan merugikan bagi komunitas tetapi termuat dalam kemampuan untuk mengekspresikan dan mengomunikasikan kepada yang lain tentang keunikan sang pembicara.” (25). Bortolini yang juga sama bersimpatiknya kepada Arendt melihat bahwa gambaran yang paling esensial dan radikal dalam pemikiran Arendt adalah “fakta tindakan, ketertampakan dan dunia bersama adalah faktor-faktor yang perlu untuk menyingkapkan sang aktor bukan hanya kepada yang lain, tetapi terutama dan pertama sekali kepada dirinya sendiri” (“Hannah Arendt”, 7). Tafsiran ini berdasarkan kata-kata Arendt sendiri yang eksplisit: “Cukup pasti bahwa sang ‘siapa’, yang tampak dengan sangat jelas dan tak-teragukan kepada yang lain, tetap tersembunyi bagi orang itu sendiri” (Human Condition, 179). Dengan kata lain, identitas personal para aktor tidak terciptakan di luar ruang publik sebagai ruang politik tetapi mereka membutuhkan ruang publik untuk membentuk diri mereka sendiri dan mendapatkan ketetapannya. Menurut Arendt, ruang publik adalah ruang realitas kemenduniaan para aktor yang mengitarinya dan memunculkan dirinya yang sejati dan terpercaya (Human Condition, 57). Dengan kata lain, menurut Arendt, “bagi kita, penampakan […] mengkonstitusi realitas” (Human Condition, 50).
Kita melihat bahwa Arendt memahami politik sebagai kondisi kemungkinan bagi “penemuan diri” atau “penyingkapan kedirian” yang meliputi: eksistensi ruang publik sebagai sebuah ruang ketertampakan dan arena interaksi; kesetaraan politis dari para pihak yang terlibat; dan, tentu saja yang paling penting, pluralitas para aktor atau, dengan kata lain, perbedaan mereka (“Hannah Arendt”, 7). Penyingkapan kebenaran akan “siapa”-nya manusia di ruang publik diperoleh melalui permintaan sang aktor kepada rekan-rekannya untuk memberikan perhatian pada tindakan dan wicaranya yang menyingkapan “siapa”-nya, dan meminta mereka mengatakan kepadanya tentang “siapa”-nya yang mereka tangkap dari tindakan dan wicara tersebut sehingga ia pun mengerti siapa dia sebenarnya. Proses pengenalan diri melalui orang-orang lain di ruang publik ini tidak pernah tuntas dan hanya akan berakhir bersama kematian. Namun masalahnya, dalam menjadikan dirinya sebagai “obyek” yang harus ditemukan dan dikonfirmasi oleh rekan-rekannya, sang aktor berisiko kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Sebagaimana dicatat Bortolini (“Hannah Arendt”, 8), paradoks ini terletak dalam fakta inilah satu-satunya cara ia mengetahui siapa ia sebenarnya; sebelum tindakan dan wicaranya terjadi di ruang publik, ia tidak benar-benar eksis sebagai seorang manusia. “Tuntutannya untuk penyingkapandirinya” hanya bisa terpenuhi dengan mempertaruhkan identitas dirinya dengan risiko kehilangan. Itulah sebabnya mengapa dalam pandangan Yunani Kuno, keberanian adalah “keutamaan politik yang pertama”. Dalam kata-kata Arendt sendiri: “Siapa pun yang memasuki ruang politik pertama-tama harus bersedia dan siap mempertaruhkan hidupnya dengan risiko, dan mencintai kehidupan secara berlebihan justru memenjarakan kebebasan” (Human Condition, 36).
Jadi, karakter ketiga Manusia Politik Arendtian dapat saya katakan adalah manusia yang eksistensinya tidak terberi, tetapi dikonstruksi dalam dan melalui politik. Konstruksi eksistensial manusia di dalam politik berarti bahwa politik ruang bagi penemuan eksistensinya (yang unik, bebas, plural, dan mortal tetapi abadi melalui narasi), sementara melalui politik berarti politik adalah sebuah perangkat epistemologis (atau semacam kategori transendental Kantian) untuk mengenal kesiapa-an manusia.
Tetapi, sekarang kita menghadapi masalah dalam penalaran Arendt: sebagaimana eksistensi manusia tidak terberi kecuali di dalam dan melalui politik, politik sendiri pun tidak terberi. Lalu bagaimana “kerumitan” ini terpecahkan? Manusia mengkonstruksi dirinya dalam sesuatu yang juga harus dikonstruksi? Saya mencoba menjawab “kebingungan Arendtian” ini dengan memakai apa yang ia terima dengan antusias dari Aristoteles yaitu keberanian, yang adalah keutamaan pertama dalam politik. Tetapi bukan sembarang keberanian, melainkan hanya yang boleh saya sebut “keberanian-politis”. Dengan kata lain, tidak semua keberanian itu politis. Keberanian-politis adalah keberanian bertindak dan berwicara (serta juga berpikir) di mana substansi dari keberaniannya itu “tertangkap” sebagai “urusan bersama” di “ruang bersama”.
Ruang publik, yaitu ruang-bersama dengan urusanbersamanya, sebagai yang saya sebut “kategori transendental” Kantian, akan menyaring sekaligus dan bersamaan apakah sebuah keberanian itu adalah keberanian politis dan apakah substansi dari keberanian itu juga politis. Hasrat sebuah kelompok—melalui demonstrasi, perdebatan dan lobi di parlemen serta lembaga ekskekutif, misalnya— untuk menjadikan kepentingan partikularnya (gabungan totalitas dari seluruh kepentingan tunggal) menjadi “kepentingan umum”, dengan menggunakan tafsiran saya terhadap pemikiran Arendt yang disajikan di sini, jelas bukan masalah dan urusan politik dan bukan keberanian politis.
Totalitarianisme, demokrasi liberal (yang berdasar pada hak pribadi atau hak kelompok, dan bukan pada “hak bersama”, kalau boleh saya usulkan istilah ini, yang dalam pandangan saya berbeda dari hak kolektif atau hak komunal), dominasi, bahkan hegemoni (termasuk dalam pengertian yang paling elegan dari Gramsci), perjuangan kelas, perjuangan kelompok-kelompok sosial semisal LGBT, gender, kelompok minoritas religius dan etnis tertentu, juga perjuangan kelompok mayoritas agama tertentu, misalnya ada, untuk menjadikan agamanya sebagai “ideologi” negara, semua itu bukan “masalah politis” dan bukan “keberanian-politis”—ini keyakinan berdasarkan tafsiran saya pada Arendt—selama keberanian mereka hanyalah mengusung hal-hal yang “tidak ada” pada seluruh pihak dalam ruang publik, dan karena “tidak ada” maka hal itu menjadi “tidak sama-sama ada” di seluruh pihak, dan karenanya “bukan kepentingan bersama”.
Kepentingan bersama berarti kepentingan yang sama-sama ada di seluruh pihak yang mengitari meja bundar ruang publik. Lalu, bagaimana dengan keunikan para aktor yang menampakkan dirinya di ruang publik? Keunikan mereka tidak terletak pada kebedaan yang tidak tertangkap oleh ruang publik—justru jika demikian tidak dapat dikatakan sebagai unik lagi, tak termengerti sebagai unik—tetapi pada proses memunculkan dan menyingkapkan diri dan esksistensi mereka. Eksistensi manusia tidak terletak pada muatan (esensi) yang ditampakkan di ruang publik, tetapi pada proses, pada kreativitas (mencipta, berarti memulai), pada kebebasan, pada keberanian.
Kritik singkat atas “Tindakan Politik” Arendtian dengan tafsiran lain atas “Manusia Gua” Plato
Kritik terhadap pemikiran politik Arendt sebanyak pembelaan terhadapnya. Dalam bagian penutup ini saya tidak berpretensi memunculkan kritikkritik itu, tetapi juga tidak bermaksud membela Arendt dengan mengambil posisi Margaret Canovan yang melakukan reinterpretasi sekaligus koreksi terhadap kritiknya sendiri terhadap Arendt dengan melakukan studi yang mendalam dan menyeluruh bukan hanya pada naskah-naskah Arendt yang diterbitkan dalam pelbagai bentuk (sebagaimana dilakukan para kritikus dan pembela Arendt pada umumnya), melainkan juga dengan membongkar serta menekuni pelbagai tulisannya yang tidak diterbitkan yang didokumentasikan dengan sangat baik oleh Perpustakaan Kongres, Washington D.C.
Naskah-naskah yang tidak diterbitkan itu sedikit banyak membuat para kritikusnya, dan juga para pembelanya, berpikir ulang ketika melakukan interpretasi terhadap pemikirannya yang dikenal mengundang perdebatan sangat panjang. Yang hendak saya kemukakan di sini adalah sebuah kritik yang hemat saya, paling tidak dari jelajah yang cukup terbatas pada pelbagai komentator Arendt, luput dari perhatian mereka (26) yang bagi saya sendiri justru adalah jantung “filsafat” politik Arendt. Di sini saya menggunakan apa yang menjadi landasan kritik Arendt terhadap filsafat politik tradisional Barat, yaitu kritiknya terhadap Plato, dalam hal ini alegori Gua, tetapi dengan tafsiran lain daripada
Pertama, tampaknya Arendt mempunyai asumsi terlalu positif terhadap politik, bahkan dengan mengikuti alur pikirannya sebagaimana telah saya ketengahkan secara runtut di atas bukan lagi tampaknya melainkan sangat jelas. Asumsi positif itu adalah bahwa politik tidak mungkin busuk dari dirinya sendiri, ia hanya busuk karena faktor di luar politik. Asumsi ini sedikit terlepas dan berbeda dari asumsi antropologisnya, sebuah implikasi yang bisa terjadi, yaitu bahwa manusia juga bisa busuk dari dirinya sendiri karena selain tindakan, manusia juga mempunyai kerja dan karya, dua hal yang potensial membusukkan manusia.
Kita sudah melihat bahwa politik adalah khas manusia, bahkan manusia tidak manusiawi kalau bukan politis, lebih lagi politik itu konstitutif bagi ke-siapa-an manusia, politik adalah perangkat epistemologis untuk mengenal manusia. Singkatnya, manusia adalah politis, tetapi bukan terberi, melainkan dikonstruksi.
Dalam upaya konstruksi itu, dua fakultas lain yaitu kerja dan karya sangat mungkin mempengaruhi tindakan sebagai fakultas politis diri manusia. Jadi, kalau manusia mengandung potensi membusuk, politik pun dengan sendirinya berpotensi membusuk bukan terutama dari luar dirinya melainkan dari dalam dirinya sendiri.
Politik yang membusuk ini tidak lagi dapat menyingkapkan kebenaran tentang siapa manusia, dan karena itu pencarian kebenaran tentang siapa manusia sangat tidak mungkin lagi didapatkan di dalam politik. Manusia harus keluar dari kepalsuan itu untuk mengenal di satu sisi kebenaran yang lain (saya tidak mengatakannya “sejati”) dan di sisi lain mengenal kepalsuan sebagai kepalsuan.
Tindakan “keluar” itu adalah sebuah tindakan eksistensial (exist berasal dari bahasa Latin ex + sistere, berdiri atau bergerak keluar). Jadi, menurut saya, tindakan sang filsuf keluar dari Gua kepalsuannya (mungkin belum disadari sebagai kepalsuan, tetapi situasi itu terasa pengap dan menyiksa, hal ini sendiri sudah sebuah kesadaran awal) adalah sebuah tindakan politis yang lain, sebuah tindakan yang tidak bisa tidak diambil ketika politik itu sendiri sudah tidak memadai sebagai modus penyingkapan kebenaran, bahkan sebagai apa yang saya sebut di atas “cara berada manusia”.
Kedua, momen kembalinya sang filsuf ditangkap Arendt sebagai momen koersif, bukan momen dialog. Sebagaimana diparafrasekan oleh Canovan, “Setelah memperoleh kebenaran, mereka [para filsuf— tambahan dari penulis] bukannya berupaya membujuk massa tetapi memaksa mereka, entah dengan menakut-nakuti mereka dengan hukuman ilahi atau dengan menggunakan pemaksaan intelektual dalam bentuk yang lebih profesional, yang memaksa mereka untuk mengikuti alur sesak penalaran deduktif” (Hannah Arendt, A Reinterpretation, 256; Between Past and Future, 107-111).
Dalam keberatan saya yang kedua ini, saya mau mengatakan dua hal. Pertama, sebagaimana tindakan sang filsuf untuk keluar (exsistere) adalah sebuah tindakan politik, demikian juga “tindakannya untuk masuk-kembali” (dalam bahasa Latin: in + sistere, bergerak ke dalam, bersikukuh, mengusahakan dengan rajin) tidak dapat tidak adalah sebuah tindakan politik. Kedua, kebersikukuhan sang filsuf (filsafat) memang mudah sekali dibaca sebagai tindakan koersif oleh manusia-manusia Gua Plato yang tinggal dalam kepalsuan itu.
Tetapi, coba bayangkan, misalnya, dua hal berikut. Pertama, filsuf yang keluar dan masuk kembali itu bukan hanya satu, melainkan dua atau tiga atau lebih, dan mereka sekarang bersama yang lain yang belum berpencerahan, maka kedatangan-kembali sang filsuf berikutnya akan disambut dengan model dialog. Mereka saling bertukar pikiran tentang kebenaran yang mereka temukan di luar Gua. Jadi, karakter koersif hanya ditangkap oleh yang belum berpencerahan, sementara yang sudah berpencerahan ditangkap sebagai dialog, komunikasi.
Kedua, filsuf yang keluar dan masuk-kembali mungkin memang hanya satu, tetapi entah bagaimana, rekan-rekannya yang berada di dalam ternyata menemukan juga jenis kebenaran lain dari yang mereka persepsi selama ini (seperti yang diharapkan Arendt), maka kedatangan-kembali sang filsuf kita dalam analisis ini akan disambut dengan dialog, bukan koersi. Persoalannya, harapan Arendt ini, dengan kembali kepada keberatan saya yang pertama di atas, dalam konteks politik yang sudah sangat busuk, tidak mungkin terjadi. Mereka butuh penebus. Tetapi penebus kita di sini berbeda dengan penebus 37 Leninian, yaitu kader (partai kader)—karena “para buruh tidak mungkin membebaskan dirinya sendiri dari kapitalisme mengingat kapitalisme sudah sangat merasuk hingga ke sendi-sendi kehidupan mereka—yaitu aktor-aktor berpencerahan tetapi yang tidak berasal dari proletar Gua Plato.
Penebus kita di sini adalah aktor internal yang gerah dengan status quo, dengan banalitas, yang mungkin belum tahu apa yang salah dengan politik dan ruang politik yang dihuninya, yang mungkin pada tahap awal hanya berkeinginan keluar saja, mengambil jarak dari realitas yang tidak lagi dapat diterima sebagai realitas; dan “melarikan diri” kepada solitudo, yang dalam kesoliterannya dan keberjarakannya menemukan mungkin bukan kebenaran sejati melainkan sekadar sebuah kebenaran yang lain; dan penebus kita ini tidak lupa akan politik, politik sebagai cara berada khas manusia, politik di mana rekan-rekannya berada; penebus kita ini tidak dapat tidak terarah untuk kembali berada-bersama-mereka, karena dalam kesoliterannya ia “merasa kehilangan”, dan kehilangan itu hanya terjadi karena ia sebelumnya sudah memiliki, yaitu memiliki “beradabersama-yang-lain”.
Kesimpulan saya adalah—sambil setuju sebagian dengan Arendt bahwa politik tidak berlangsung di ruang privat tetapi kepolitikan ruang publik mempengaruhi kehidupan di ruang privat dan bukan sebaliknya— politik juga tidak hanya berlangsung di ruang publik. Ada sebuah ruang lain yang hemat saya menjadi arena politik yang sejati, sebuah ruang yang saya kira tidak pernah dibicarakan para filsuf politik, yaitu sebuah ruang yang saya namakan “ruang antara” (in-between space). Konsep ini “terpaksa” saya konstruksi ketika saya terenyak dalam sebuah diskusi dengan rekan-rekan di Kapal Perempuan yang, dalam konteks advokasi keadilan gender, menolak dikotomi ruang publik-ruang privat.
Di satu sisi saya melihat bahaya penolakan itu (bahaya totalitarianisme), tetapi di sisi lain ruang publik kita secara faktual selain menjadi situasi Gua Plato juga menjadi ruang publik yang formal tetapi secara material tidak. Misalnya, parlemen sebagai formalitas ruang publik, tetapi aktor-aktor di dalamnya sibuk membuka situs pornografi ketika bersidang, atau semua serius 38 berdialog, tetapi yang mereka dialogkan adalah kepentingan-kepentingan tertentu kelompok mereka, bukan kepentingan bersama; itu sama sekali bukan gambaran ruang publik sebagai ruang bersama. Politik tidak lagi berlangsung di sana. Politik berlangsung dalam momen sang manusia Gua Plato “keluar” dan kemudian “masuk-kembali”.
Ruang-antara yang saya maksudkan di sini mungkin bukan sebuah ruang dalam arti yang sebenarnya (spasial), melainkan lebih sebagai sebuah “momen”, ruang yang dimengerti dalam kategori proses-dalam-kemewaktuan.
Jadi, manusia politik kita sekarang adalah, melampaui manusia politik Arendtian, manusia yang berada di dunia (politik) bersama yang lain (solider) yang menyingkapkan dirinya melalui tindakan dan wicara (vita activa), tetapi selalu melakukan tindakan keluar (exsistere) ke ruang pemikiran (vita contemplativa) dan selalu juga melakukan tindakan ke dalam (insistere) untuk mendialogkan dan mempraktikkan “kebenaran yang lain” (kembali lagi vita activa), selalu begitu, terutama dalam konteks banalitas, kepalsuan dan status quo Gua Plato.
Manusia politik adalah manusia-manusia penghuni “ruang antara”, yang selalu risau ketika berada di ruang publik, apalagi ruang privat, dan selalu risau pula ketika berada di ruang kontemplatif. Sebagaimana kita dapat membayangkan Sisifus bahagia, dan momen kebahagiaan itu terjadi ketika ia turun gunung untuk mengangkat kembali batunya ke puncak, maka momen kebahagiaan manusia politik kita di sini adalah, bukan saat ia keluar atau saat “menemukan kebenaran”, melainkan saat ia bertindak masuk-kembali, tetapi bukan juga saat ia berada di dalam Gua politik.***
Disclaimer:
Sumber Tulisan dari Buku Manusia Perempuan Laki-laki, Salihara 2011. Tulisan ini sudah dimuat di laman website https://www.berandanegeri.com, tanggal 26 Maret 2022.