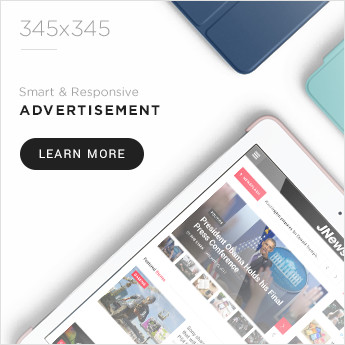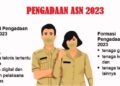Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
Pengajar Ilmu Sosiologi Agama di Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ketika Gunung Lewotobi Laki-Laki dan Ile Lewotolok memuntahkan isi perutnya, gemuruh alam tak hanya meluluhlantakkan rumah dan ladang serta aset-aset kehidupan lainnya, tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat Flores Timur dan Lembata akan makna kehidupan, penderitaan, dan harapan. Di balik gumpalan awan panas dan serpihan lapili, hadir dinamika yang lebih dalam: pergulatan spiritual dan sosial yang dijalin melalui benang-benang iman, tradisi, dan solidaritas.
Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di lereng gunung, setiap letusan bukan semata bunyi dentuman kehancuran, melainkan gema panggilan ilahi yang menggetarkan kesadaran kolektif. Ia bukan sekadar malapetaka, tetapi menjadi altar spiritual tempat manusia menakar iman, merajut makna, dan menyusun ulang harapan. Di tengah gemuruh lava dan langit yang memerah, komunitas diuji bukan hanya secara fisik, tetapi dalam keteguhan batin menghadapi duka yang tak terelakkan. Dari sudut pandang sosiologi agama, bencana semacam ini bukan hanya tragedi geologis. Ia adalah juga drama iman, tempat keyakinan tampil bukan sebagai dogma kaku, melainkan sebagai pelindung psikososial, jembatan antara trauma dan ketenangan, antara reruntuhan dan kebangkitan. Di sanalah, spiritualitas menjelma menjadi lentera yang membimbing langkah-langkah rapuh menuju pemulihan.
Dalam pusaran krisis yang mengguncang jiwa dan raga, agama tampil sebagai penopang ganda. Di satu sisi, ia merangkul individu dalam kepasrahan yang menyejukkan hati, memberi ruang untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari rencana ilahi yang tak selalu dapat dijangkau akal. Di sisi lain, ia menggerakkan kekuatan sosial yang melampaui sekat-sekat perbedaan, memanggil insan beriman untuk saling menopang lewat doa bersama, gotong royong, dan pelukan spiritual yang menghidupkan harapan. Seperti yang ditegaskan oleh Prof. Sulfikar Amir dari NTU Singapore, agama bukan sekadar ritual, tapi mekanisme bertahan yang menjembatani trauma dengan ketenangan, menjadikan iman sebagai fondasi ketangguhan komunitas.
Di tengah selubung abu vulkanik yang menenggelamkan langit dan membungkam harapan, masyarakat yang terpapar letusan tidak hanya berlari menyelamatkan diri. Mereka menyatukan langkah dalam ikatan spiritual yang tak tergoyahkan. Masjid dan gereja darurat berubah menjadi ruang suci, tempat kesedihan berpadu dengan kekuatan batin. Di sana, zikir mengalun lirih bersandingan dengan pujian yang menggema, melahirkan simfoni iman yang menembus pekatnya duka. Mereka tidak sekadar berlindung dari amukan alam, tetapi menyalakan cahaya dalam gelapnya ketidakpastian. Iman menjadi denyut kolektif, menyatukan jiwa-jiwa yang rapuh dalam pelukan solidaritas yang melampaui batas-batas keyakinan. Dalam doa yang mengalir dari bibir-bibir yang berdebu, harapan pun kembali ditanam di tanah yang retak.
Namun, dalam denyut ketakutan yang menyelimuti lereng-lereng gunung, tidak semua langkah menuju keselamatan diterima tanpa resistensi. Sosiologi agama membuka realitas paradoks: bahwa iman yang menjadi sumber ketenangan, kadang juga menjadi dinding penghalang mitigasi. Seperti diungkap oleh Achmad Zainal Arifin dari UIN Sunan Kalijaga, tafsir spiritual masyarakat sering bertabrakan dengan pendekatan ilmiah yang berbasis data dan analisis risiko. Ketika gunung dianggap sebagai “rumah roh” atau situs sakral yang tak boleh ditinggalkan, maka himbauan evakuasi menjadi seolah membongkar ruang suci. Keyakinan akan kepasrahan (“yang penting pasrah”) justru melahirkan sikap pasif yang meredam urgensi kesiapsiagaan. Di titik ini, spiritualitas yang mestinya membebaskan, kadang justru melanggengkan kerentanan. Maka, dialog antara iman dan ilmu tak bisa lagi ditunda. Ia harus dibangun dari akar budaya, agar keselamatan dan keyakinan bisa bersanding tanpa saling menafikan. Fenomena ini serupa dengan kasus Mbah Maridjan di Merapi—tokoh spiritual yang memilih tetap di rumah meski berada dalam zona merah. Ia percaya bahwa kehendak Tuhan lebih penting daripada instruksi teknis. Tragedi itu menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi harus berani merangkul dimensi spiritual, bukan sekadar menyuguhkan data ilmiah dan skenario teknokratik.
Mengacu pada pemikiran Aguste Comte, masyarakat yang berada dalam fase teologis cenderung menafsirkan fenomena alam termasuk bencana seperti letusan gunung api sebagai perwujudan langsung dari kehendak supranatural. Dalam konteks Flores Timur dan Lembata, warisan pemikiran ini tampak hidup dan berdenyut dalam kesadaran kolektif. Ketika Gunung Lewotobi atau Ile Lewotolok bergemuruh, banyak warga tidak sekadar melihatnya sebagai proses geologis, melainkan sebagai teguran atas kelalaian moral, ujian atas keteguhan iman, atau bahkan sebagai panggilan ilahi untuk bertobat dan kembali ke jalan spiritual. Tafsir semacam ini tidak lahir dari kekosongan, melainkan berakar pada relasi mendalam antara manusia, tanah leluhur, dan kekuatan gaib yang diyakini mengatur keseimbangan kosmis. Dalam pandangan mereka, abu yang menyelimuti desa bukan hanya partikel debu, melainkan simbol dari peringatan Tuhan yang menyentuh batin dan memanggil jiwa untuk kembali berpaut pada nilai-nilai transenden.

Dalam renungan mendalam Said Nursi, bencana bukanlah murka semata, melainkan undangan lembut dari Tuhan agar manusia kembali menengadah dan memperhalus jiwanya. Ia melihat penderitaan sebagai jalan terang menuju keagungan Ilahi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memurnikan dan mendidik batin. Dengan menggabungkan mistisisme cinta dari Rumi dan teologi keadilan dari Al-Ghazali, Nursi membingkai bencana sebagai medium transenden yang menyentuh nurani. Dalam gelapnya kabut letusan, manusia justru menemukan cahaya spiritual, sebab derita membuka ruang refleksi yang tak tercipta dalam kelapangan. Bagi Nursi, semakin dalam luka, semakin dekat pintu Tuhan terbuka. Maka, kesakitan bukan akhir, melainkan awal perjalanan jiwa menuju penghayatan hakiki atas cinta dan keadilan Ilahi.
Letusan gunung di Flores Timur dan Lembata telah mengguratkan pelajaran mendalam yang tak boleh hanya diresapi sebagai narasi penderitaan semata, tetapi sebagai peta spiritual menuju masa depan yang lebih tangguh dan bermartabat. Agama, yang selama ini hadir sebagai pelipur duka dan penghibur luka, ditantang untuk melampaui perannya yang pasif dan tampil sebagai kekuatan edukatif dan transformatif. Seperti diungkap melalui gagasan teologi fungsional ala Abdul Mustaqim, umat beragama tidak cukup hanya berdoa setelah bencana terjadi. Lebih dari itu, mereka harus menjadi pelaku perubahan yang sadar akan ekologi, cerdas dalam kesiapsiagaan, dan aktif dalam membangun budaya tanggap terhadap potensi bahaya.
Ini bukan sekadar ajakan untuk merangkul alam, tetapi dorongan spiritual untuk memperbarui cara pandang terhadap ciptaan Tuhan. Menanam pohon, menghargai siklus bumi, menyusun sistem peringatan dini, semuanya itu adalah bentuk ibadah jika dipahami dalam kerangka keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, Flores Timur dan Lembata tidak hanya akan dikenal sebagai tanah yang kuat menghadapi letusan, tetapi sebagai wilayah di mana iman dan ilmu berjalan berdampingan menuju kebangkitan yang penuh makna.
Dalam lanskap pascabencana yang sarat luka dan harapan, ritual keagamaan tidak cukup hanya menjadi gema permohonan keselamatan yang menggema di langit kelabu. Ia perlu berinkarnasi menjadi gerakan ekologis yang nyata—menjadi langkah-langkah kecil namun bermakna yang menghidupkan kembali bumi yang terluka. Ketika doa mengalir dari hati yang khusyuk, ia seharusnya menjelma menjadi aksi kolektif: penanaman pohon di lereng rawan longsor sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan, pembangunan rumah ibadah tahan gempa sebagai wujud tanggung jawab spiritual terhadap keselamatan umat, serta pendidikan generasi muda bahwa iman dan ilmu tidak bertentangan, melainkan berpadu dalam misi menyelamatkan ciptaan. Di sinilah teologi menjelma menjadi ekologi, dan spiritualitas beralih dari langit ke tanah: menyentuh realitas dan memulihkan keberlangsungan.
Letusan gunung adalah pesan purba yang ditulis dalam bahasa bumi dalam gemuruh, dalam retak tanah, dalam semburan abu yang membungkam nyanyian pagi. Tapi masyarakat Flores Timur dan Lembata tidak menjawab dengan keluhan, melainkan dengan bahasa langit: doa yang lirih, solidaritas yang menyala, dan harapan yang mereka tanam di antara puing-puing yang belum dingin. Di balik reruntuhan itu, spiritualitas menemukan bentuk paling tulusnya: hening namun bertenaga, sunyi namun menyinari. Sosiologi agama mengajarkan bahwa keyakinan bukan sekadar pelarian, tetapi denyut kehidupan yang memampukan manusia berdiri kembali. Dan, di sanalah harapan tumbuh, bukan dari janji kekuasaan, tetapi dari kekuatan batin yang dibangun satu doa dalam satu langkah. Flores Timur dan Lembata tidak sekadar selamat: ia sedang bangkit, dengan mata yang memandang ke langit dan kaki yang menapak tanah dengan penuh keberanian.(*)