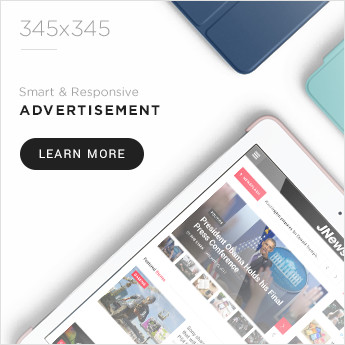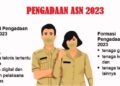Aksinews.id/Lewoleba — Peringatan Hari Pahlawan di Lembata tahun ini tidak hanya menjadi ajang mengenang jejak perjuangan masa lalu, tetapi juga ruang refleksi bagi generasi masa kini untuk mempertanyakan kembali arah keberpihakan pembangunan dan kualitas kesetaraan sosial di daerah.
Pondok Perubahan menghadirkan sebuah dialog terbuka bertema “Kapan Kita Setara? Suara Muda untuk Iklim Sosial Lembata,” yang mempertemukan para aktivis muda, perempuan, penyandang disabilitas, jurnalis, pemerhati sosial, NGO, hingga perwakilan pemerintah.
Forum ini menjadi ruang penting untuk menyuarakan kegelisahan kolektif atas situasi alam dan struktur sosial Lembata yang terus berubah dan semakin menantang kehidupan kelompok rentan.

Lembata menghadapi tekanan perubahan iklim yang semakin nyata. Data Pena Bulu Foundation tahun 2024 menunjukkan penurunan tutupan mangrove hingga 40 persen, musim tanam yang tidak lagi dapat diprediksi, serta meningkatnya ancaman abrasi dan kekeringan. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir kehilangan sumber mata pencaharian, sementara kelompok perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka berhadapan dengan berlapis tantangan: akses terbatas terhadap sumber daya, beban kerja domestik yang meningkat, serta minimnya ruang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Situasi ini diperparah oleh iklim sosial yang rentan akibat derasnya informasi tidak akurat, hoaks, dan polarisasi yang membuat hubungan antara masyarakat, pemerintah, komunitas adat, dan media semakin renggang. Keretakan ini menunjukkan bahwa bukan hanya ekosistem alam yang rapuh, tetapi juga ekosistem sosial yang menopang kehidupan bersama sedang tidak baik-baik saja.
Dalam forum diskusi, para narasumber memaparkan berbagai temuan dan pengalaman yang menggambarkan kompleksitas persoalan ketidaksetaraan di Lembata. Ibu Erlin Dangu dari PLAN Indonesia menegaskan bahwa “perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi realitas hari ini yang memukul kelompok rentan dua kali lebih keras.”Forum Jurnalis Lembata (FJL), Alexander Taum memberikan gambaran tentang bagaimana media lokal juga berperan dalam memperkuat atau melemahkan kesadaran publik tentang isu-isu penting seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Menurutnya, “disrupsi digital membuat banyak media terjebak dalam produksi konten viral yang dangkal. Akibatnya, isu krusial mengenai perempuan, disabilitas, dan perubahan iklim terpinggirkan.”
Ia menekankan pentingnya menjaga kedalaman jurnalistik dan menghadirkan liputan-liputan yang memberi ruang bagi suara kelompok marginal.
Perspektif akar rumput disampaikan Ramli Leuwayan dari Lembaga Abdi Masyarakat Indonesia, yang menggambarkan upaya anak muda di desa-desa Kedang membangun epistemic community untuk menciptakan ruang belajar, berbagi gagasan, dan membaca ulang persoalan sosial di lingkungan mereka. Menurutnya, banyak pemuda kini mulai melakukan riset kecil, diskusi komunitas, serta advokasi sederhana di tingkat desa.
Namun temuan yang muncul cukup memprihatinkan, “perempuan masih jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, struktur adat masih sangat maskulin, dan ketimpangan sosial tetap kuat.” Beberapa desa sudah mulai memberi dukungan untuk merekronstruksi struktur sosial ini seperti menyediakan ruang perpustakaan atau ruang belajar, tetapi belum menjadi kebijakan berkelanjutan.

Perbincangan mengenai budaya adat menjadi salah satu bagian paling penting dalam diskusi. Para narasumber sepakat bahwa adat Lamaholot dan identitas kultural Lembata adalah nilai luhur yang harus dijaga. Namun dalam praktiknya, pengambilan keputusan adat masih didominasi laki-laki, sementara perempuan lebih sering berada di posisi yang dipertimbangkan, bukan menentukan. Meskipun secara simbolik perempuan dihargai melalui struktur budaya tertentu seperti belis, dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap terbebani peran domestik dan minim akses ruang publik.
Erlin Dangu menegaskan, “Solusinya bukanlah menghapus adat, melainkan membuka ruang refleksi dan dialog di antara tokoh-tokoh adat agar struktur pengambilan keputusan lebih inklusif bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas”.
Dampak perubahan iklim terhadap dinamika keluarga dan pola migrasi juga menjadi sorotan penting. Mama Tini dari P2PA menggambarkan bagaimana banyak orang tua di Ile Ape terpaksa bermigrasi karena gagal panen dan kebutuhan untuk mencari sumber pemasukan ekonomi yang baru. Migrasi ini menjadi strategi bertahan hidup, namun meninggalkan konsekuensi berat bagi anak-anak yang ditinggalkan. Mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan putus sekolah.
Ramli menambahkan bahwa penelantaran anak sering bermula dari kemiskinan ekstrem, bukan semata keputusan buruk keluarga. Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus dipahami sebagai persoalan struktural yang menuntut respons kebijakan publik yang komprehensif, bukan sekadar solusi kasus per kasus.
Di sisi lain, Alexander Taum menyampaikan bagaimana pemerintah daerah diharapkan memperkuat perannya. Meski pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan langkah maju, banyak program belum berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Media lokal juga dihadapkan pada tantangan kapasitas dan tekanan kerja yang membuat isu mendalam kurang mendapat ruang. Situasi ini menciptakan lingkaran setan: kelompok rentan tidak terdengar suaranya, kebijakan tidak peka terhadap kebutuhan mereka, dan ketimpangan terus berulang.
Sementara itu, rekomendasi strategis muncul untuk memperkuat gerakan anak muda dalam advokasi isu iklim dan sosial. Ibu Erlin mendorong penyusunan roadmap gerakan lima tahun agar komunitas anak muda memiliki arah kerja yang jelas dan berkelanjutan, bukan sporadis. Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik di sekolah, komunitas keagamaan, dan kelompok desa, serta pembangunan basis data sederhana untuk memperkuat advokasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa suara anak muda harus hadir sebagai suara substantif, bukan sekadar formalitas dalam forum-forum konsultasi.
Dalam sesi tanya jawab, muncul refleksi kritis dari peserta, di antaranya Om Eman Krova, yang menyatakan bahwa “diskusi ini sesungguhnya sedang menggugat struktur peradaban lokal yang tidak setara.” Menurutnya, pertanyaan “kapan kita setara?” tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi lensa untuk membaca ulang berbagai ketimpangan sosial yang telah lama dianggap biasa. Ia menyoroti bagaimana tradisi patriarki membatasi ruang gerak perempuan dan kebutuhan membangun narasi besar yang menjadi payung bagi tindakan-tindakan aplikatif seperti penyediaan fasilitas publik yang aman dan sensitif gender.
Dua pertanyaan penting juga muncul dari perwakilan Komunitas Tuli Lembata (Kak Denis dan Kak Eti), yaitu “bagaimana pemerintah, LSM, dan kelompok Tuli dapat bekerja sama membangun Lembata yang inklusif?”, serta “bagaimana peran LSM yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dalam mendukung kebutuhan kelompok disabilitas?”. Pertanyaan ini disampaikan melalui Kak Emil Fernandez selaku Juru Bahasa Isyarat, dan langsung mengguncang suasana forum karena menunjukkan bahwa kelompok Tuli ingin terlibat aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar menjadi objek program.
Momen ini menjadi momen yang menyentuh, keberanian mereka mengajukan pertanyaan tentang hak, akses, dan kesempatan bagi kelompok Tuli menjadi simbol paling kuat dari perjuangan menuju kesetaraan. Dari ruang tersebut, terlihat jelas bahwa kesetaraan tidak hadir karena diberikan, tetapi lahir ketika mereka yang selama ini berada di pinggir berani melangkah ke pusat ruang dialog.
Forum yang berlangsung selama beberapa jam itu menutup dengan pemahaman baru: kesetaraan adalah sebuah proses panjang yang hanya dapat terwujud ketika semua orang diberi ruang berbicara, didengar, dihargai, dan dilibatkan. Suara-suara yang muncul malam itu, terutama dari kelompok muda dan disabilitas, menjadi pengingat bahwa inklusivitas bukan janji masa depan, melainkan tindakan yang dimulai di sini dan sekarang. Melalui suara mereka, publik Lembata melihat sebersit harapan tentang sebuah masyarakat yang terus bergerak menuju keadilan iklim dan keadilan sosial, dua hal yang tidak pernah dapat berjalan terpisah. (Gavel L-Pondok Perubahan)