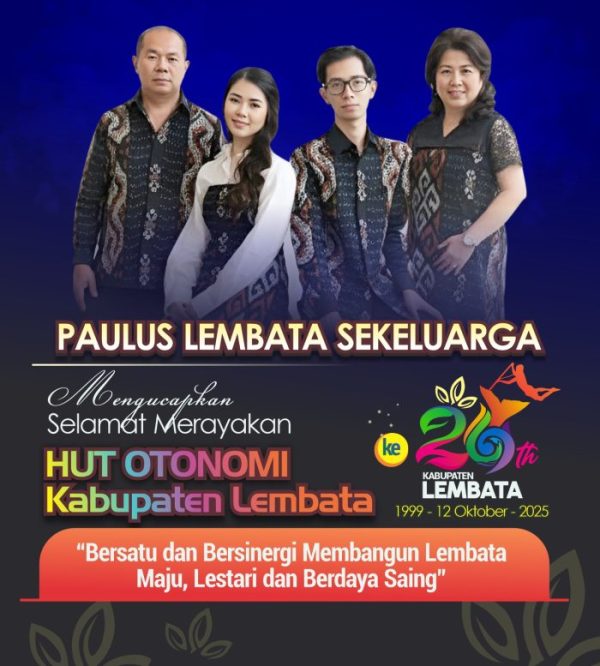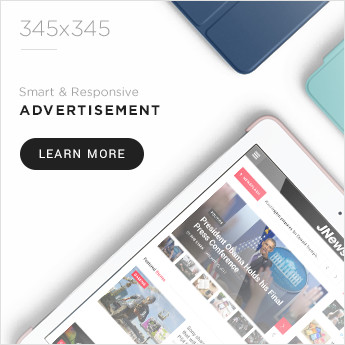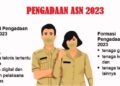Oleh: Laurensius Bagus
Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Ketika Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, publik kembali diingatkan bahwa masalah sampah bukan sekadar urusan kebersihan kota, tetapi juga bagian dari agenda besar transisi energi Indonesia.
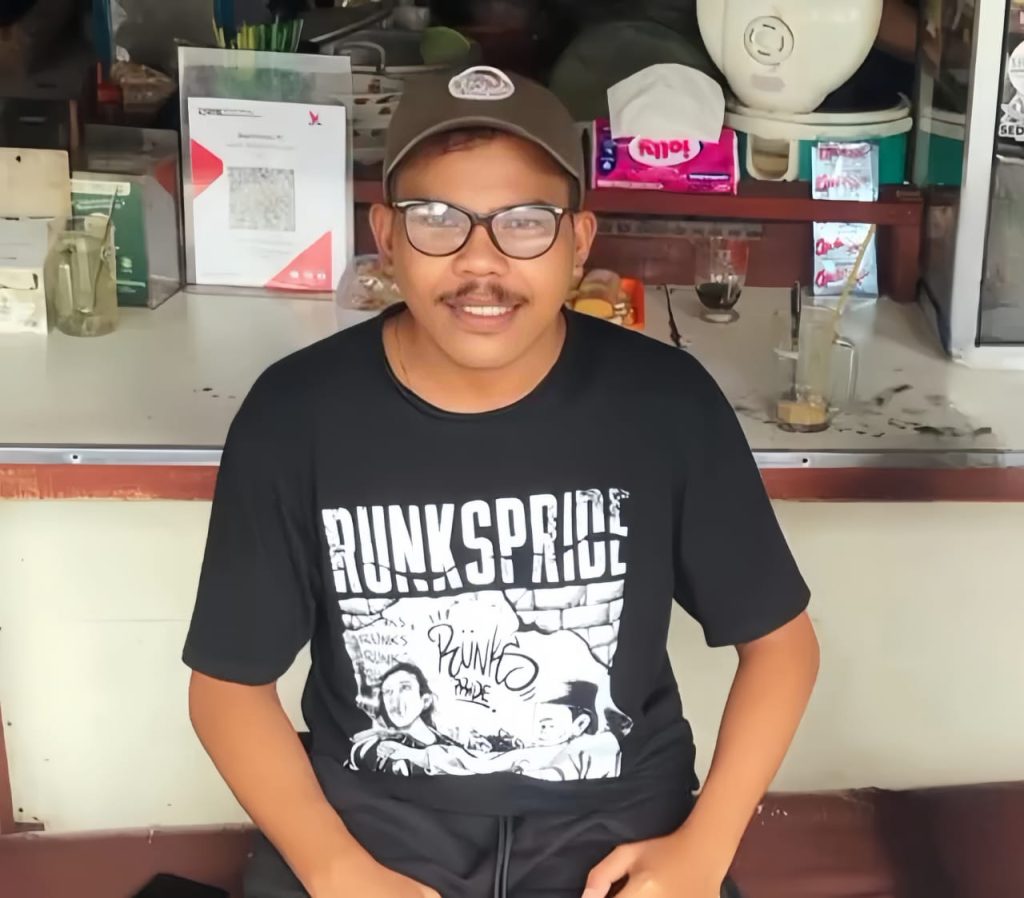
Kebijakan ini menandai langkah ambisius: menjadikan timbunan sampah — yang selama ini dianggap beban lingkungan — sebagai sumber energi baru yang berkelanjutan. Namun di balik semangat itu, muncul pertanyaan penting: apakah seluruh daerah di Indonesia siap menghadapi transformasi ini?
Ledakan Sampah dan Janji Energi Baru
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional pada tahun 2023 mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun, dengan komposisi terbesar berasal dari rumah tangga (sekitar 40%). Dari jumlah itu, baru 39 persen yang berhasil terkelola, sisanya menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), sungai, atau pesisir.
Perpres 109/2025 menjadi payung hukum baru untuk mendorong Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE). Pemerintah menargetkan empat jenis energi dapat dihasilkan dari sampah: listrik, bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk ikutan lainnya.
Untuk skema listrik, PT PLN (Persero) diwajibkan membeli hasil listrik dari PSE dengan harga tetap USD 0,20 per kWh, agar investor memiliki kepastian finansial.
Kebijakan ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan Net Zero Emission 2060. Namun, implementasinya di lapangan tidak sesederhana membangun mesin pembakar sampah atau waste-to-energy incinerator. Tantangan terbesar justru ada di tahap paling dasar: pengelolaan sampah itu sendiri.
Ketimpangan Infrastruktur dan Kapasitas Daerah
Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat timpang. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Denpasar, sistem pengumpulan dan pemrosesan sudah relatif teratur, meski TPA-nya mulai penuh. Namun di banyak kota kecil dan daerah pedesaan, sampah masih ditangani secara tradisional: dibakar, ditimbun, atau dibuang sembarangan.
Keterbatasan lahan, minimnya fasilitas daur ulang, dan rendahnya literasi pemilahan sampah membuat konsep sampah jadi energi sulit dijalankan secara merata.
Sebagian besar proyek waste-to-energy hanya mungkin dilakukan di daerah dengan volume sampah minimal 1.000 ton per hari, sementara banyak kabupaten di Indonesia bahkan belum mencapai separuh angka itu.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas di lapangan. Tanpa skema adaptif bagi daerah kecil, program energi dari sampah berisiko hanya tumbuh di kota besar dan gagal menjangkau wilayah lain.
Peluang Energi dari Skala Komunitas
Meski begitu, peluang tetap terbuka melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Sekitar 60% sampah Indonesia adalah sampah organik yang bisa diolah menjadi biogas atau pupuk. Teknologi sederhana seperti biodigester dapat dikembangkan di tingkat rumah tangga atau komunitas.
Beberapa daerah mulai melangkah ke arah ini. Di Kabupaten Klungkung, Bali, misalnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan universitas untuk mengubah limbah pasar menjadi gas bio untuk kebutuhan dapur umum. Sementara di Yogyakarta dan Bandung, sejumlah komunitas warga sudah mengelola bank sampah yang menghasilkan refuse derived fuel (RDF), bahan bakar padat pengganti batu bara untuk industri semen.
Pendekatan berbasis komunitas seperti ini lebih realistis, terutama di wilayah yang belum siap dengan teknologi pembakaran besar. Ia juga memberi nilai sosial tambahan: menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesadaran ekologis warga.
Menjembatani Keadilan Energi dan Lingkungan
Dalam konteks transisi energi nasional, keadilan menjadi kata kunci. Pembangunan infrastruktur hijau tidak boleh hanya berpusat di Jawa atau kota besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah, dari perkotaan hingga pelosok, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi energi bersih sesuai kapasitasnya.
Tiga langkah penting perlu segera diambil:
- Mendorong inovasi teknologi kecil-menengah yang murah dan bisa diterapkan di berbagai skala.
- Mensinergikan kebijakan energi dan pengelolaan sampah agar tidak berjalan sendiri-sendiri di tingkat kementerian maupun daerah.
- Meningkatkan partisipasi publik — karena tanpa pemilahan sampah di rumah tangga, semua teknologi canggih akan sia-sia.
Penutup: Dari Krisis ke Peluang Hijau
Kebijakan energi dari sampah adalah upaya besar menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Tetapi, kebijakan itu hanya akan berhasil jika menyentuh akar persoalan: kesadaran warga, pemerataan infrastruktur, dan keberpihakan terhadap daerah yang tertinggal.
Indonesia tidak kekurangan teknologi, melainkan sering kekurangan koordinasi dan keberpihakan.
Sampah bukan sekadar beban, tetapi juga cermin bagaimana kita memperlakukan bumi ini — apakah sebagai ladang yang bisa diperbarui, atau sekadar tempat pembuangan dari gaya hidup kita sendiri.
Dari tumpukan sampah, sesungguhnya kita bisa membangun energi baru — bukan hanya listrik, tetapi juga kesadaran untuk hidup lebih adil dan lestari. (*)