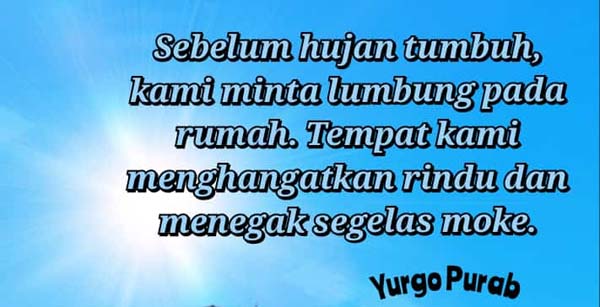Ruang Pengakuan
Senyum gadis itu rimpu, sampai-sampai aku bersimpuh pada detak nafasnya yang memburu resah. Dari tatapan matanya, ada gelisah yang menyoal di sana.
Aku mendapatinya selepas pagi, saat hujan baru tumbuh di batas aspal. Kerling matanya mengguyur lebat, ku saput tisu dari saku celanaku, dan menyintuh permukaan matanya yang mulai basah.
Tak ada yang memerhatikan kami, hanya langit yang masih utuh menemani pagi.
Setelah melewati kecakapan panjang, aku baru mengerti. Bahwa Ia baru saja bertemu seorang lelaki, yang menyapu air matanya dan mengatakan kepadanya, “Pergilah, dosamu sudah ku ampuni. Dan mulai dari sekarang, janganlah berbuat dosa lagi.”
Hingga saat ini senyum membiak dalam hidupnya, seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia menawarkan senyum yang sama kepadaku.***

Pura-Pura Mencintai
Perempuan itu baru saja menggisar rambutnya, setelah berpapas dengan lelaki tambun di pinggir pematang sawah. Rasa rindunya meledak dadak, seperti bedak yang menempel tebal di wajahnya. Tapi sayang, kerap lelaki itu pura-pura mencintai karena mencintai kerap juga pura-pura.***
Segelas Dalam Bicara
Sebelum hujan tumbuh, kami minta lumbung pada rumah. Tempat kami menghangatkan rindu dan menegak segelas moke. Dari rumah yang kami tiba, hujan menumpahkan air mata gelisah. Tampak kami pun memayung kisah, yang terjulur lewat nasi-nasi sisa. Seperti itulah percakapan tentang hujan dalam segelas hangat kopi. Di tepi sore jelang, kami menatap risih, sebab mata mengatup lengah. Segelas dalam bicara, setelah meneguk; kami terpacung jauh. Kata-kata mengalir hangat dari tenggorok menuju hal yang tak tuntas, mungkin juga tak jelas.***